Dinasti Shailendra: Leluhur Buddhisme Mahayana di Indonesia (Bahasa Indonesia)

Sebuah lukisan Borobudur, kompleks candi yang dibangun oleh Dinasti Shailendra. Sekarang menjadi lokasi wisata dan ziarah yang terkenal di dunia, dan telah ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO.
Shailendra (yang dieja Sailendra, Syailendra atau Selendra) adalah turunan dari gabungan kata-kata Sanskerta ‘Śaila’ dan ‘Indra’ yang bermakna “Raja Pegunungan”. Dinasti Shailendra, yang muncul di Jawa (Indonesia) selama abad ke-8 Masehi, sangat dipengaruhi oleh budaya India dan memainkan peran penting dalam kebangkitan budaya di daerah tersebut. Sebagai penyebar Buddhisme Mahayana yang berkuasa, Shailendra membangun monumen Buddhis di seluruh Jawa Tengah. Salah satu monumen, yaitu stupa besar Borobudur, telah dinyatakan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO dan merupakan salah satu situs paling populer di Jawa bagi para peziarah dan wisatawan saat ini.

Kepulauan Indonesia di Asia Tenggara, di sini ditunjukkan dengan warna krem, terdiri atas lebih dari 17.000 pulau. Dua yang luasnya lebih besar adalah Jawa dan Sumatra. Di berbagai masa dalam sejarah, Dinasti Shailendra adalah keluarga penguasa Kerajaan Medang di Jawa Tengah dan Kerajaan Sriwijaya di Sumatra. Klik untuk memperbesar.
Shailendra adalah para pelaut yang berkuasa di seantero samudra Asia Tenggara. Meskipun mereka adalah kerajaan maritim, Dinasti ini juga merupakan pembudidaya pertanian dan sangat bergantung pada pertanian padi di Dataran Kedu. Dataran Kedu, juga dikenal sebagai Lembah Sungai Progo, terletak di antara Gunung Sumbing dan Gunung Sundoro di barat, serta Gunung Merbabu dan Gunung Merapi di timur. Sekarang, lokasi ini berada di Kabupaten Magelang dan Temanggung, Jawa Tengah, Indonesia.

Dataran Kedu ditandai di peta Pulau Jawa, sebagaimana ketika masa Kerajaan Medang (abad ke-8 sampai 11 M). Klik untuk memperbesar.
Pada berbagai masa dalam sejarah, dinasti penguasa samudra ini rupanya berasal dari keluarga penguasa Kerajaan Medang di Jawa Tengah dan Kerajaan Sriwijaya di Sumatra. Pemain kunci dalam sejarah Shailendra meliputi:
- Dapunta Selendra, pendiri Dinasti Shailendra
- Sri Sanjaya (diperdebatkan; sebagai gantinya beberapa mengatakan bahwa ia adalah anggota Dinasti Sanjaya)
- Rakai Panangkaran, penganut Buddhis (memerintah 760 – 775 M)
- Dharanindra, Penakluk Musuh yang Gagah Berani (memerintah 775 – 800 M)
- Samaratungga, pemersatu kerajaan (memerintah 812 – 833 M)
- Pramodhawardhani dan Rakai Pikatan (memerintah 840-an – 856 M)
- Balaputradewa, donatur Universitas Nalanda (memerintah 860 -? CE)
- Sri Kesari Warmadewa, keturunan Dinasti Shailendra yang menjadi penguasa di Bali (memerintah 882 – 914 M)
- Maharaja Sanggrama Vijayatunggavarman, raja terakhir
Daftar ini sama sekali belum lengkap, juga belum terselesaikan karena banyaknya informasi tentang Dinasti Shailendra yang menjadi bahan perdebatan oleh para cendekiawan dan sejarawan. Sejarawan telah berusaha merekonstruksi daftar definitif dari penguasa Shailendra dan wilayah mereka, tetapi mereka belum dapat mencapai konsensus. Tantangan yang mereka hadapi meliputi:
- Kurangnya informasi. Informasi yang diperoleh dari prasasti seringkali sangat terbatas dan sulit untuk diuraikan.
- Shailendra tampaknya telah memerintah banyak kerajaan seperti Kalingga, Medang dan Sriwijaya, dan seringkali kerajaan dan tempat bertumpang tindih.
- Ejaan nama dan tempat juga sangat bervariasi, karena perbedaan bahasa, penggunaan julukan, pergolakan dan perubahan politik, fakta bahwa peristiwa ini telah terjadi begitu lama di masa lampau, dll.
Meski demikian, adanya daftar tentatif sebagai rujukan, berguna ketika mencoba memahami sejarah Shailendra yang luas beserta dampaknya terhadap wilayah kekuasaan dan agama Buddha.
- Sumber Historis
- Asal Muasal
- Penyatuan Kekuasaan
- Era pasca-Balaputradewa
- Kerajaan-Kerajaan Utama
- Penguasa Penting
- Candi
- Artefak
- Galeri
Sumber Historis
Sebagian besar informasi sejarah tentang Dinasti Shailendra dapat diperoleh dari prasasti batu yang ditemukan di Indonesia, semenanjung Melayu, sampai sejauh India, di mana ada sebutan historis dari Shailendra yang dieja dalam berbagai versi. Prasasti adalah ukiran tulisan pada sesuatu yang terbuat dari batu atau logam; salah satu contoh populer yang dikenal banyak orang adalah Batu Rosetta.
Prasasti-prasasti yang mendokumentasikan sejarah Shailendra sebagian besar merupakan piagam yang ditulis dalam berbagai bahasa seperti bahasa Sanskerta, Jawa Kuna, Bali Kuna, Melayu Tua, dan bahkan dalam bahasa Sunda Kuna. Prasasti ini menjadi dasar bagi dokumentasi kronologis sejarah Indonesia. Beberapa prasasti adalah salinan yang ditulis beberapa abad setelah penanggalan aslinya, sebagian besar selama periode Majapahit. Meskipun aslinya hilang, salinan umumnya dianggap membawa keakuratan historis dari aslinya.
Terlepas dari prasasti batu dan tembaga, ada juga teks-teks yang disusun di atas daun palem (dikenal sebagai lontar) ng telah ditemukan di Jawa, Bali dan Sunda. Teks-teks ini sebagian besar adalah tentang sejarah yang ditulis dengan gaya sastra klasik.

Naskah teks daun lontar dari Indonesia.
Sumber-sumber lain tentang Dinasti Shailendra berasal dari teks-teks Tiongkok, Muslim, dan India. Dari Tiongkok, Shailendra dirujuk dalam Catatan Kerajaan (Pen Chi), yang merupakan catatan terperinci tentang hadiah atau upeti yang diterima oleh Kaisar Tiongkok dari berbagai utusan asing. Pejabat Pengadilan Tiongkok mencatat nama raja beserta turunannya dan utusannya dari negeri asing, hadiah yang diterima, dan tanggal kapan diterima.
Sumber informasi lain dari Tiongkok adalah Sejarah Dinasti, di mana tertulis di pemberitahuan (Chuan) tentang catatan masing-masing negara. Pen Chi dan Chuan tidak saling berhubungan, maka dengan demikian memberikan akurasi catatan yang lebih besar akan peristiwa yang terjadi. Catatan Tiongkok memainkan peran penting dalam mencatat sejarah Indonesia, terutama selama periode sebelum abad ke-8 M ketika sebagian besar informasi sejarah tentang Jawa dan Bali dapat terlacak asal-usulnya di catatan Tiongkok ini.
Berbeda dengan orang Tiongkok yang mencatat peristiwa, catatan Muslim (kebanyakan dalam bahasa Persia dan Arab) sering ditulis oleh pelancong dan geografer yang lebih tertarik pada ciri-ciri negara daripada kejadian yang didokumentasikan. Dengan demikian, catatan-catatan ini memberikan perspektif yang berbeda tentang tanah air Indonesia kuno.
Dari India, prasasti tembaga memberikan informasi penting tentang Jawa dan Sumatra dari abad ke-9 M hingga abad ke-11 M. Naskah-naskah awal yang ditulis dalam bahasa Sanskerta dan Pali, juga ada sejak masa awal Masehi; yang menyebutkan berbagai bagian dari kepulauan Indonesia, menunjukkan bahwa India mengenal mereka dengan baik.
Beberapa dokumen dari Kamboja dan Vietnam memberikan sedikit informasi namun penting tentang Indonesia zaman dahulu dan akhirnya, beberapa sumber Yunani, seperti dari geografi Claudius Ptolemy (juga dikenal sebagai Klaudius Ptolemaeus; s. 100 – 170 M), juga menyebutkan beberapa nama tempat di Indonesia.
Selain dari sumber-sumber informasi asing di atas, masih ada banyak prasasti dan dokumen sejarah yang belum diuraikan dan diterjemahkan, seperti prasasti batu yang ditemukan di Sumatra yang masih sebagian dalam penerjemahannya. Tidak ada keraguan bahwa kekayaan sejarah Indonesia akan terungkap lebih jauh jikalau lebih banyak sejarawan dan pemerintah Indonesia mengambil peran yang lebih besar dalam proses penerjemahan.
Dinasti Shailendra merupakan masa yang penuh keagungan dalam sejarah Indonesia, ketika dengan gaya pelautnya menaklukkan sebagian besar kepulauan Indonesia dan memperluas perdagangan serta hubungan bilateral ke India, Tiongkok, dan Asia Tenggara. Dalam prediksinya, Raja Sri Sanjaya meminta pewaris tahtanya, Rakai Panangkaran (yang juga dikenal sebagai Rakai Panaraban), untuk memeluk Buddhisme Mahayana, yang berdampak lestari selama periode pemerintahan Dinasti Shailendra dan seterusnya. Selama masa ini, Dinasti Shailendra mendirikan banyak situs sakral dan bersejarah, seperti kompleks Candi Borobudur, sekaligus menghasilkan banyak artefak relijius.
Prasasti Batu
Menurut prasasti batu yang diketemukan di Sumatra, Dinasti Shailendra kemungkinan telah memerintah Kerajaan Medang di Jawa Tengah, serta Kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Shailendra membuat prasasti batu menggunakan tiga bahasa: Jawa Kuna, Melayu Tua dan Sanskerta, baik dalam aksara Kawi atau skrip pra-Nāgarī.
Penggunaan berbagai bahasa ini telah memunculkan spekulasi tentang kemungkinan asal usul Shailendra. Penggunaan bahasa Jawa Kuna tampaknya menunjukkan bahwa kedudukan politisnya ada di tanah Jawa, sedangkan penggunaan bahasa Melayu Tua tampaknya menempatkan asal mereka di Sumatra; sementara itu, penggunaan bahasa Sanskerta sangat menunjukkan sifat resmi dan/atau religius dari peristiwa yang digambarkan prasasti batu tersebut.
Prasasti Sojomerto (sekitar 725 M) yang ditemukan di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, bertuliskan ‘Dapunta Selendra’ dan ‘Selendranamah’. Nama ‘Selendra’, ejaan lain dari ‘Shailendra’, menunjukkan bahwa Dapunta Selendra bisa jadi adalah pendiri Shailendra di Jawa Tengah. Prasasti itu menunjukkan bahwa keluarga tersebut pada awalnya adalah penganut Hindu Saiwa, salah satu aliran utama dalam tradisi Hindu dengan Siwa sebagai pujaan dewa utama mereka. Praktek ini terlaksana sebelum memeluk Buddhisme Mahayana.
Prasasti Kalasan (sekitar 778 M) adalah prasasti paling awal yang ditemukan di Jawa Tengah. Dengan menyebut Shailendra sebagai ‘Śailēndravamśatilaka ’, kita berkenalan dengan Rakai Panangkaran, penguasa yang memperingati peresmian Candi Kalasan (atau Kuil Kalasan), sebuah candi Buddhis yang didedikasikan untuk Dewi Tara.
Prasasti Kelurak (sekitar 782 M) dan prasasti Karangtengah yang kemudian (sekitar 824 M) juga menyebutkan nama ‘Śailēndravamśatilaka’.
Prasasti Ligor (juga dikenal sebagai prasasti Chaiya; sekitar 775 M), yang ditemukan di semenanjung Melayu, dan prasasti Nalanda (sekitar 860 M), yang ditemukan di India, termaktub di dalamnya tulisan nama ‘Shailendra’. Isinya menunjukkan adanya kemungkinan Rakai Panangkaran sebagai pembuat prasasti Ligor dan penakluk Kerajaan Sriwijaya, yang berbasis di Sumatra tetapi berpengaruh pada sebagian besar Asia Tenggara.
Kemungkinan Asal Muasal Dinasti Shailendra
Kemungkinan Asal Muasal Dinasti Shailendra

Dataran Kedu di Pulau Jawa
Asal usul Shailendra yang sebenarnya merupakan suatu topik perdebatan, meskipun telah diketahui bahwa kemunculan mereka berasal dari Dataran Kedu di Jawa Tengah. Ada pendapat bahwa mereka berasal dari Sumatra, India atau bahkan Kamboja. Namun, penelitian baru-baru ini mendukung kemungkinan bahwa Dinasti Shailendra berasal dari Jawa, terlepas dari hubungan kuat mereka dengan semenanjung Thailand-Melayu dan Kerajaan Sriwijaya di Sumatra.
India
Bahwa Shailendra awalnya berasal dari Kalingga di India Timur pertama kali digagas oleh Dr Ramesh Chandra Majumdar, seorang sarjana India yang menulis 11 volume Sejarah dan Budaya Rakyat India, yang membahas Periode Weda hingga tahun 1955. Ia menyusun ini setelah 26 tahun pembelajaran, penelitian, dan suntingan.

Sejarawan India Dr Ramesh Chandra Majumdar
Klaim Dr Majumdar juga sama dengan Nilakanta Sastri, seorang sejarawan terkenal di India Selatan, dan J.L. Moens, seorang pakar otodidak dari Belanda yang juga pemerhati ikonografi artefak sejarah Hindu-Jawa. Moens menjelaskan bagaimana Shailendra berasal dari India dan menetap di Palembang, Indonesia. Di kemudian hari, dengan kedatangan Dapunta Hyang Sri Jayanasa dari Sriwijaya pada 683 M, Shailendra dipaksa oleh Dapunta Hyang dan pasukannya untuk bermigrasi ke Jawa.
Kamboja
Teori lain, yang diajukan oleh cendekiawan Prancis George Cœdès, mengklaim adanya hubungan antara Shailendra dengan Kerajaan Funan di Kamboja, yang meyakini hubungan itu terletak pada kesamaan dalam nama-nama mereka.
Nama ‘Shailendra’ adalah turunan dari kata-kata Sanskerta ‘Śaila’ dan ‘Indra’. Ketika digabungkan, arti namanya adalah ‘Raja Gunung’. Menurut Cœdès, para penguasa Funan dirujuk dengan gelar yang mirip yaitu ‘Tuan Gunung’. Namun, banyak spesialis sejarah Kamboja menolak teori ini, karena tidak ada bukti historis gelar tersebut dipergunakan pada masa periode Funan.
Jawa, Indonesia
Teori saingan lainnya menempatkan Shailendra sebagai dinasti Jawa asli, dengan Dinasti Sanjaya sebagai percabangan dari Shailendra. Ini bermula dari anggapan bahwa Raja Sri Sanjaya dan anak-anaknya adalah anggota keluarga Shailendra, yang semula adalah penguasa Saiwa di Kerajaan Medang. Lewat Rakai Panangkaran yang beralih memeluk Buddhisme Mahayana, Shailendra menjadi terhubung dengan agama Buddha.

Naskah Abad ke-16 M, Carita Parahyangan
Dituliskan dalam Carita Parahyangan, manuskrip abad ke-16 M, sebuah kisah tentang Raja Sri Sanjaya yang sakit-sakitan menuruti sentimen masyarakat atas pilihan mereka akan agama Buddha yang cinta damai, daripada Siwa yang ditakuti yang disembah oleh keluarga kerajaan. Raja Sri Sanjaya memerintahkan putranya untuk masuk agama Buddha. Prasasti Raja Sankhara juga rupanya menjelaskan peralihan Panangkaran memeluk agama Buddha karena ketakutan rakyatnya terhadap keyakinannya pada Siwa. Sayangnya, prasasti Raja Sankhara telah hilang sehingga ini tidak dapat dikonfirmasi.
Kerajaan Sriwijaya (Sumatra, Indonesia)
Beberapa cendekiawan mengklaim bahwa kerajaan Buddhis Sriwijaya terlibat dalam kemunculan Dinasti Shailendra. Klaim-klaim ini menekankan hubungan dalam lindungan Buddhisme Mahayana dan pernikahan silang antara kaum Shailendra dan Sriwijaya, sebagaimana tertulis dalam prasasti batu Ligor. Beberapa prasasti, yang ditulis dalam Bahasa Melayu Tua, semakin memperkuat hubungan yang diklaim dengan Sriwijaya.
Lebih jauh, prasasti Sojomerto (725 M) menyebut pendiri Dinasti Shailendra sebagai Dapunta Selendra, memposisikannya sebagai leluhur Shailendra. Mengingat bahwa prasasti Sojomerto ditulis dalam bahasa Melayu Tua (meskipun ditemukan di pantai utara Jawa Tengah), maka kemungkinan fakta adalah Shailendra berasal dari Sumatra atau terhubung dengan Kerajaan Sriwijaya, karena baik Raja Sriwijaya, Dapunta Hyang Sri Jayanasa, dan Dapunta Selendra keduanya dijuluki sebutan kehormatan yang sama ‘Dapunta’, sebuah gelar yang digunakan oleh raja-raja Sriwijaya yang sebelumnya.
Penyatuan Kekuasaan
Aliansi yang saling menguntungkan antara Shailendra dan Sriwijaya ditempa dan dipertahankan melalui cara-cara damai, termasuk pernikahan antara Raja Shailendra Samaratungga dan Dewi Tara, putri Raja Dharmasetu dari Sriwijaya. Dengan kerjasama yang menguntungkan ini, kedua kerajaan menghilangkan persaingan dan menyebarluaskan akses perdagangan yang mejangkau skala internasional.
Pernikahan antara Raja Samaratungga dan Putri Dewi Tara diduga melahirkan dua anak – seorang putri, Pramodhawardhani (atau Sri/Cri Kahulunan) dan seorang putra, sang pewaris tahta Balaputradewa.
Nampak seperti para leluhurnya, Pramodhawardhani sangat spiritual. Didokumentasikan dalam prasasti Karangtengah 824 M bahwa Pramodhawardhani mendirikan Candi Jinalaya yang suci. Kebetulan saja, prasasti itu juga menyebutkan pendirian bangunan suci Buddhis lainnya, yaitu Venuvana (artinya ‘Hutan Bambu’), oleh Raja Dharanindra untuk menampung jasad kremasinya.
Lebih jauh lagi, dalam prasasti Tri Tepusan, yang bertanggal 842 M, di dalamnya menceritakan tentang Pramodhawardhani yang membebaskan penduduk setempat dari pajak tanah sehingga tambahan penghasilan mereka dapat digunakan untuk pemeliharaan Bhumisambhara (yang lebih dikenal sebagai Borobudur).
Pramodhawardhani menikahi Rakai Pikatan dari Dinasti Sanjaya, yang nantinya akan menjadi penyebab berakhirnya pemerintahan sang adik, Balaputradewa, di Jawa Tengah. Pada tahun 852 M terjadi perang saudara antara kedua orang itu, setelah Balaputradewa menemukan bahwa Rakai Pikatan mengerahkan para bangsawan setempat untuk melawannya. Perang saudara berakhir dengan kekalahan Balaputradewa dan ia terpaksa kembali ke Kerajaan Sriwijaya di Sumatra, di mana ia mengambil peran sebagai pemimpin tertinggi mereka.

Sebuah lukisan karya G.B. Hooijer (sekitar 1916 – 1919) dari Borobudur seperti yang terlihat di masa kejayaannya. Klik untuk memperbesar.
Periode sejarah Shailendra ini, serta asal usul leluhur mereka, diperdebatkan. Beberapa sejarawan percaya bahwa Samaratungga adalah putra dan pewaris Raja Samaragrawira sementara sejarawan lainnya seperti N.J. Krom dan George Cœdès menganggap Samaragrawira dan Samaratungga sebagai pribadi yang sama.
Belakangan seorang sejarawan bernama Slamet Muljana dari Indonesia, tidak setuju dengan hal ini. Ia berteori bahwa Samaragrawira sebenarnya memiliki dua putra – Samaratungga, yang lebih tua dan Balaputradewa, yang lebih muda. Klaimnya didukung oleh:
- Prasasti Malang, yang menyatakan bahwa Samaratungga hanya memiliki satu putri (dan tidak memiliki putra)
- Prasasti Nalanda, yang mencatat Balaputradewa sebagai putra Samaragrawira, yaitu sebagai saudara, dan bukan putra, dari Samaratungga.
Jadi, menurut Pak Muljana, Balaputradewa bukan putra Samaratungga tetapi sebenarnya adalah adik laki-lakinya. Jika ini benar, maka itu akan memberi Balaputradewa klaim yang lebih besar untuk berkuasa dan bertahta di Jawa; seandainya Samaratungga meninggal tanpa seorang putra dan pewaris yang sah, maka adik lelakinya yang jadinya mengambil alih tahta setelah kematiannya, bukan putrinya.
Maka dengan memposisikan Balaputradewa sebagai saudara laki-laki, dan bukan anak laki-laki, hal ini menantang legitimasi Pramodhawardhani dan pemerintahan suaminya, Rakai Pikatan.
Era Pasca-Balaputradewa
Setelah masa pemerintahan Balaputradewa berakhir, muncullah raja Shailendra yang lain, yaitu Sri Kesari Warmadewa, yang merupakan raja pertama di Bali yang meninggalkan prasasti tertulis. Ia menulisnya di Pilar prasasti Belanjong di Sanur, Bali dan menyatakan bahwa dirinya adalah anggota Dinasti Shailendra yang memimpin ekspedisi militer ke Bali untuk mendirikan pemerintahan Buddhis Mahayana.
Jadi, seperti kaum Shailendra yang memerintah sebelumnya, Sri Kesari adalah seorang raja Buddhis. Sri Kesari dianggap sebagai pendiri Dinasti Warmadewa. Oleh karena itu Pilar prasasti Belanjong, yang bertajuk 914 M, menarik hubungan antara Dinasti Warmadewa dengan Shailendra.
Shailendra juga menjaga hubungan dengan Kerajaan Chola di India Selatan, sebagaimana didokumentasikan dalam banyak prasasti India Selatan. Sebuah prasasti abad ke-11 M menyebutkan wihara Buddhis di India yang dibangun oleh Raja Sriwijaya pada tahun 1005 M, yang memberikan pendapatan pajak sebagai biaya pemeliharaannya. Namun, pada tahun 1025 M, hubungan antara kedua dinasti itu hancur.
Raja Rajendra Chola menginvasi Kekaisaran Shailendra, yang berbasis di Sriwijaya, menaklukkan beberapa wilayah penguasa Shailendra dan menghancurkan mereka yang berada di jalur lintasan. Maharaja Sanggrama Wijayatunggavarman, raja terakhir Shailendra, ditangkap dan disandera. Tanpa pemimpin, Shailendra tidak pernah benar-benar pulih dari kehancuran besar-besaran ini, secara efektif mengakhiri dinasti yang berkuasa di Sumatra ini.
Kerajaan Chola dan Shailendra mampu memulihkan hubungan yang lebih damai sebelum akhir abad ke-11 M. Pada tahun 1090 M, piagam baru diberikan kepada Sriwijaya, prasasti terakhir yang menyebutkan Shailendra. Namun, karena tidak memiliki pewaris Shailendra yang sah, keluarga kerajaan dari Sriwijaya yang lain menggantikannya naik tahta, dimulai dengan Maharaja Sri Deva yang dinobatkan dan, bersama dengan itu, sebuah dinasti baru mulai memerintah Sriwijaya.

Relief timbul di Borobudur menggambarkan adegan istana Raja dan Ratu diikuti oleh rakyatnya, berdasarkan istana kerajaan Shailendra.
Rentang Waktu Kejadian-Kejadian di Dinasti Shailendra
Berikut ini adalah tonggak penting dan kejadian terkait dengan Dinasti Shailendra, yang dapat memberikan beberapa kejelasan tentang aktivitas dan warisan keluarga yang mulia ini:
- 674 M – Dapunta Selendra, pendiri Dinasti Shailendra dikisahkan telah lahir.
- 683 M – Dapunta Hyang Sri Jayanasa tiba di Kerajaan Sriwijaya.
- Abad ke-8 M – Kerajaan Medang, juga dikenal sebagai Kerajaan Mataram, pada awalnya didirikan oleh Raja Sri Sanjaya dari Dinasti Sanjaya.
- 775 M – Rakai Panangkaran melepaskan tahtanya untuk menemukan kedamaian spiritual dan berfokus pada hal-hal relijius.
- 775-800 M – Pada masa pemerintahan Raja Dharanindra, Dinasti Shailendra memperluas kebijakan perdagangan mereka ke Kerajaan Sriwijaya. Selain itu, Raja Dharanindra terkenal karena meluncurkan berbagai perang yang berhasil. Selama puncak kejayaan Kerajaan Medang, pengaruhnya mencapai Bali, Sumatra, Kamboja, dan Filipina saat ini.
- 792 M – Samaratungga mengambil alih tahta Kerajaan Sriwijaya.
- c. 852 M – Damainya hidup berdampingan antara Shailendra dan Dinasti Sanjaya berakhir dengan perang saudara, ketika Rakai Pikatan dan Balaputradewa, putra Raja Samaratungga, saling bertarung. Balaputradewa dikalahkan dan dipaksa untuk meninggalkan Jawa, mengambil tempat tinggal di Sumatra di Kerajaan Sriwijaya di mana ia menjadi penguasa tertinggi.
- 860 M – Prasasti Nalanda dibuat sebagai penjelasan bagaimana Raja Kekaisaran Pala, Dewapaladewa, memberikan izin kepada Sri Maharaja (yang juga dikenal sebagai Balaputradewa) untuk membangun sebuah wihara di area Nalanda.
- 1005 M – Sebuah prasasti abad ke-11 M menyebutkan wihara Buddhis di India yang dibangun oleh Raja Sriwijaya, yang menghibahkan pendapatan pajak sebagai biaya pemeliharaannya.
- 1025 M – Hubungan antara Kerajaan Chola dan Shailendra, yang berpusat di Sriwijaya, rusak. Raja Rajendra Chola menginvasi dan menaklukkan beberapa wilayah Shailendra. Raja terakhir Shailendra yaitu Maharaja Sanggrama Vijayatunggavarman, disandera. Kerajaan Chola dan Shailendra mampu memulihkan hubungan yang lebih damai sebelum akhir abad ke-11 M tetapi tanpa adanya pemimpin, Dinasti Shailendra tidak dapat benar-benar pulih.
Kerajaan-Kerajaan Utama yang Terhubung Dengan Dinasti Shailendra
Selama rentang abad ke-8 M dan ke-9 M, pemerintahan Dinasti Shailendra umumnya diyakini hanya terbatas di Jawa Tengah, sedari zaman Rakai Panangkaran hingga Raja Samaratungga. Namun, prasasti yang baru saja ditemukan mengungkapkan masa pemerintahan yang mungkin lebih lama.
Mulai dari abad ke-7 M dengan rujukan tentang kedaulatan di prasasti Sojomerto, hingga awal abad ke-11 M ketika Dinasti Shailendra dikalahkan oleh Raja Rajendra Chola, nampaknya di berbagai masa dalam sejarah, Shailendra memerintah baik Kerajaan Medang maupun Kerajaan Sriwijaya. Area kerajaan-kerajaan ini berhubungan dengan apa yang kita sebut sekarang sebagai Jawa dan Sumatra. Dari waktu ke waktu, kesetiaan dan perkawinan silang dengan keluarga Sriwijaya yang berkuasa, meleburkan kedua keluarga dinasti ini, membuat Shailendra dapat memerintah kedua kerajaan kuno tersebut pada waktu yang berbeda.
Profesor Boechari, seorang sejarawan dan pembuat epigrafi Indonesia, dahulu berusaha untuk membuat daftar asal muasal Dinasti Shailendra berdasarkan prasasti Sojomerto, sementara itu, sejarawan seperti Slamet Muljana dan Profesor Poerbatjaraka mengarahkan perhatian pada periode pertengahan dan setelahnya. Sejarawan lain menghubungkan Shailendra dengan Dinasti Sanjaya dan Sriwijaya berdasarkan prasasti dan naskah Carita Parahyangan.
Kerajaan Medang
Kerajaan Medang, juga dikenal sebagai Kerajaan Mataram, awalnya didirikan oleh Raja Sri Sanjaya dari Dinasti Sanjaya di abad ke-8 M. Prasasti Canggal (732 M), yang ditulis dengan aksara Pallawa, mencatat pembangunan lingam (simbol Siwa) sesuai instruksi raja. Sejarawan percaya bahwa temuan ini menunjukkan Medang pada mulanya adalah kerajaan Hindu.
Prasasti Canggal juga menyatakan bahwa Raja Sri Sanjaya adalah putra dari saudari Raja Sanna. Raja Sanna, penguasa Jawa sebelumnya, tewas dalam pertempuran. Kerajaan itu jatuh ke dalam kekacauan sampai Raja Sri Sanjaya mengambil alih, mendirikan Kerajaan Medang, mengalahkan penguasa lokal dan memulihkan keharmonisan di Pulau Jawa. Ia dikisahkan memiliki banyak kualitas yang mengagumkan, termasuk penguasaan taktik militer, pengetahuan tentang kitab suci, dan mahir dalam seni bela diri.
Setelah Raja Sri Sanjaya wafat, Rakai Panangkaran menggantikannya. Secara umum diyakini bahwa ia adalah putra atau keponakan Raja Sri Sanjaya, dan Raja Sri Sanjaya meminta pewaris tahtanya memeluk Buddhisme Mahayana.
Pengaruh Dinasti Shailendra tumbuh dengan kecepatan yang signifikan karena keberhasilan kebijakan perdagangan mereka. Awalnya, Kerajaan Medang sangat bergantung pada pertanian padi dan kegiatan agrikultur lainnya, tetapi mereka kemudian beralih bisnis perdagangan maritim. Pada masa pemerintahan Raja Dharanindra (memerintah 775 – 800 M), Dinasti Shailendra memperluas kebijakan perdagangan mereka ke Kerajaan Sriwijaya. Selain itu, Raja Dharanindra dikenal melaksanakan perang yang berhasil. Selama puncak kejayaan Kerajaan Medang, pengaruh mereka sampai ke Bali, Sumatra, Kamboja, dan Filipina saat ini.
Temuan-temuan arkeologis mengungkapkan bahwa pada masanya, Kerajaan Medang kondisinya makmur, padat penduduk, dan sangat canggih. Pada akhir abad ke-8 M, kerajaan telah mengembangkan arsitektur dan seni Jawa yang khas, yang dapat dilihat hari ini di Candi Borobudur, Sewu, Kalasan dan Prambanan yang terkenal se-dunia.
Shailendra dikenal sangat piawai dalam politik. Sebagai contoh, penguasa Shailendra Samaratungga meminang Dewi Tara, putri Raja Sriwijaya Dharmasetu, sehingga menjalin hubungan yang saling menguntungkan antara kedua kerajaan. Bagi Raja Dharmasetu, kerjasama yang baru saja dikembangkan ini menjadikan Kerajaan Medang yang cepat berekspansi tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka. Pada saat yang sama, bagi Raja Samaratungga, pernikahan itu membuat Dinasti Shailendra mendapat akses ke posisi strategis perdagangan internasional Sriwijaya.

Candi Hindu Prambanan yang indah
Namun demikian, setelah Raja Sri Sanjaya wafat, pengaruh Dinasti Sanjaya terus memudar sampai Raja Samaratungga dari Dinasti Shailendra mengatur pernikahan politik antara putrinya, Pramodhawardhani dan Rakai Pikatan, pangeran Dinasti Sanjaya. Pada masa pemerintahan Rakai Pikatan dan Pramodhawardhani, agama Hindu sekali lagi mendominasi Kerajaan Medang.
Pada pertengahan abad ke-9 M, kebersamaan yang damai antara Shailendra dan Dinasti Sanjaya berakhir dengan perang saudara, ketika Rakai Pikatan dan Balaputradewa, putra Raja Samaratungga, saling bertarung pada tahun 852 M. Sayangnya Balaputradewa, yang juga merupakan saudara ipar Rakai Pikatan, dikalahkan dan harus mundur ke tanah air ibunya, Kerajaan Sriwijaya, untuk menjadi penguasa di sana.
Kejadian ini, beserta naiknya Rakai Pikatan ke tampuk kekuasaan, menandai dimulainya pemerintahan Dinasti Sanjaya di Kerajaan Medang. Selama masa pemerintahan mereka, para penguasa Sanjaya membangun banyak candi Hindu, termasuk Candi Prambanan, yang dianggap sebagai candi Hindu terbesar di Asia Tenggara.
Kerajaan Sriwijaya
Kerajaan Sriwijaya dahulu adalah kerajaan Buddhis yang mendominasi sebagian besar kepulauan Melayu-Indonesia dari 650 hingga 1377 Masehi. Ia dianggap sebagai pusat penting bagi perluasan agama Buddha sehingga bahkan guru Buddhis yang terkenal, Atisha pergi ke Sriwijaya untuk belajar dengan Suvarṇadvipa Dharmakīrti.
Apa yang kita ketahui tentang Kerajaan Sriwijaya sebagian besar berasal dari prasasti batu yang ditulis dalam bahasa Melayu Tua, terutama Prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuwo, Telaga Batu dan Prasasti Kota Kapur. Menurut prasasti-prasasti ini, kota Palembang di Sumatra kemungkinan besar adalah ibukota Kerajaan Sriwijaya. Ini terlihat dari selungkup persegi panjang yang dikelilingi oleh parit, membentuk pemukiman atau kuil yang dikenal sebagai Venuvana (artinya ‘Hutan Bambu’) yang disebutkan dalam prasasti Karangtengah 824 M.

Ilustrasi seorang seniman menggambarkan penguasa Dapunta Hyang Sri Jayanasa
Prasasti itu juga menceritakan kisah seorang pemimpin perang bernama Dapunta Hyang Sri Jayanasa yang bertarung melawan lawannya dan mengumpulkan dukungan dari kota-kota tetangga di sepanjang Sungai Musi. Akibatnya, hal ini mengarahkan pada pembentukan Kerajaan Sriwijaya. Dapunta Hyang menjadi pendiri dan raja pertama Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya menyebarkan agama Buddha, menetapkan agama ini di daerah taklukkan mereka seperti Jawa dan wilayah Melayu.
Hubungan bilateral antara Sriwijaya dan Kerajaan Medang semakin menguat melalui pernikahan Dewi Tara, putri Raja Dharmasetu dari Sriwijaya dengan Raja Samaratungga dari Medang. Samaratungga kemudian mengambil alih tahta Sriwijaya pada 792 M. Menurut beberapa prasasti, ikatan pernikahannya dengan Dewi Tara memberinya seorang putri, Pramodhawardhani dan seorang putra, Balaputradewa.
Kerajaan Sriwijaya menikmati kemakmuran karena lokasinya yang strategis bagi perdagangan maritim. Pelabuhan mereka menyediakan koneksi antara Tiongkok, Asia Tenggara dan India. Selain itu, kedekatannya dengan muara Sungai Musi memungkinkan untuk pertanian berlimpah di tanah lokal yang subur. Orang Tiongkok sering menyebut Kerajaan Sriwijaya sebagai Jinzhou, atau “Pantai Emas”, karena cadangan emas yang besar ditemukan di kerajaan.
VIDEO: Menghidupkan Kembali Masa Kehidupan era Kerajaan Sriwijaya
Or view the video on the server at:
https://video.tsemtulku.com/videos/SriwijyaEmpire-4.mp4
Kerajaan Sriwijaya juga terkenal sebagai pusat praktik Buddhisme Vajrayana. Menurut prasasti Talang Tuwo (684 M), raja Sriwijaya adalah seorang penguasa relijius yang mengaitkan dirinya dengan kekuatan seorang Bodhisattwa. Sriwijaya sendiri tidak meninggalkan banyak artefak arkeologis Buddhis tetapi menjadi terkenal sebagai pusat pembelajaran Buddhis bagi para cendekiawan dan biksu, terutama di kota Palembang.
Bukti keberadaan Kerajaan Sriwijaya dapat dilacak hingga abad ke-7 M. Seorang biksu dari Dinasti Tang, I-tsing, menulis bahwa ia mengunjungi Kerajaan Sriwijaya pada tahun 671 M selama enam bulan untuk mempelajari tata bahasa Sanskerta dan bahasa Melayu. Dari sana ia melanjutkan perjalanannya untuk belajar agama Buddha di universitas terkenal Nalanda, Bihar, di tempat yang sekarang disebut India. Setelah menyelesaikan pendidikannya selama 11 tahun di universitas, ia kembali ke Kerajaan Sriwijaya dalam perjalanan kembali ke Tiongkok.
I-tsing tinggal di Palembang selama dua tahun untuk menerjemahkan berbagai sutra Sanskerta asli ke dalam bahasa Tiongkok. Dia kemudian melakukan perjalanan ke Tiongkok pada 689 M untuk mendapatkan kertas dan tinta karena dia tidak dapat menemukannya di Sriwijaya, dan ia kembali pada tahun yang sama. Pada 695 M, ia membawa kembali sekitar 400 teks terjemahan ajaran Buddha ke Tiongkok. Dia juga menulis dua buku harian perjalanan berjudul Catatan Praktik Buddha yang Dikirim Pulang dari Laut Selatan dan Ziarah Biksu dari Dinasti Tang, untuk meringkas petualangannya selama 25 tahun di Kerajaan Sriwijaya dan India.
“… Banyak raja dan kepala suku di pulau-pulau di Samudra Selatan kagum dan percaya pada [agama Buddha], dan hati mereka tertuju untuk mengumpulkan tindakan yang baik. Di kota berbenteng Bhoga [Palembang, ibukota Sriwijaya] para bhiksu Buddhis berjumlah lebih dari 1.000, batinnya mengarah pada pembelajaran dan praktik-praktik yang baik. Mereka menyelidiki dan mempelajari semua mata pelajaran yang ada seperti di Kerajaan Tengah [Madhya-desa, India]; aturan dan upacara sama sekali tidak berbeda. Jika seorang bhiksu Tiongkok ingin pergi ke Barat untuk mendengar (ceramah) dan membaca [tulisan suci asli], ia lebih baik tinggal di sini selama satu atau dua tahun dan mempraktikkan sila dengan tepat, baru kemudian melanjutkan ke India Tengah.”
Sumber: Catatan Praktik Buddhis I-tsing yang Dikirim Pulang dari Laut Selatan, juga dikenal sebagai Nanhai Jigui Neifa Zhuan
Kerajaan Sriwijaya menghasilkan banyak cendekiawan Buddhis terkemuka, termasuk Suvarṇadvipa Dharmakīrti, seorang guru lojong dan bodhicitta yang terkenal pada abad ke-10 M. Ia terkenal sebagai guru Atisha Dipamkara Shrijñana, yang belajar di bawah bimbingan Suvarṇadvipa selama 12 tahun.

Peta Kerajaan Sriwijaya
Kemerosotan kerajaan Sriwijaya dimulai pada tahun 1025 M setelah Raja Rajendra Chola dari Tamil Nadu di India Selatan meluncurkan serangkaian serangan di Kerajaan Sriwijaya. Dia bermaksud menjarah kekayaan kerajaan. Serangan terus menerus Raja Rajendra sangat melemahkan dominasi Sriwijaya, akhirnya menghasilkan pembentukan kerajaan regional yang lebih kecil seperti Kediri, yang memfokuskan ekonomi mereka pada pertanian alih-alih perdagangan pesisir. Kerajaan Sriwijaya yang lemah akhirnya dikalahkan oleh Kerajaan Majapahit yang mayoritas Hindu.
VIDEO: Mengapa Wangsa Chola Menyerbu Kerajaan Sriwijaya?
Or view the video on the server at:
https://video.tsemtulku.com/videos/WhyDidTheCholasInvadeTheSrivijayaEmpire.mp4
Penguasa Penting Dinasti Shailendra
Dapunta Selendra, Sang Pendiri
Menurut prasasti Sojomerto, Dinasti Shailendra dimulai oleh Dapunta Selendra, yang mendaulatkan diri dan keluarganya di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dapunta Selendra dikisahkan lahir pada tahun 674 M.

Kabupaten Batang, Jawa Tengah
Dapunta Selendra digambarkan sebagai seorang Hindu Saiwa. Secara umum disepakati bahwa anggota dari Dinasti Shailendra yang berikutnya memeluk Buddhisme Mahayana. Kesamaan gelar antara Dapunta Selendra dan Dapunta Hyang Sri Jayanasa telah membuat para sejarawan percaya bahwa ada hubungan di antara mereka, atau (keduanya) orang yang sama karena ‘Dapunta’ adalah gelar yang digunakan oleh raja-raja Sriwijaya sebelumnya.
Ada beberapa sumber yang mengklaim bahwa raja Shailendra pertama yang diketahui bernama Bhanu, termasuk sejarawan John Villiers yang menyebutkan dalam bukunya:
“… ketika raja Sailendra [Bhanu] yang pertama diketahui muncul.”
Sumber: J. Villiers, Sudostasien von der Kolonialzeit Hal. 96
Klaim tentang Raja Bhanu didasarkan pada prasasti Hampran. Namun, Profesor Boechari, seorang ahli epigraf dan arkeolog Indonesia, percaya bahwa klaim Bhanu sebagai raja Shailendra pertama tidak meyakinkan karena dalam prasasti, Bhanu tidak menggunakan gelar ‘Maharaja’ seperti raja-raja Shailendra lainnya.
Rakai Panangkaran, Penganut Buddhis
(memerintah antara 760 – 775 M)
Setelah Raja Sri Sanjaya wafat, prasasti Kalasan menyatakan bahwa ia digantikan oleh Rakai Panangkaran yang juga dikenal sebagai Rakai Panabaran atau Maharaja Dyah Pancapana Kariyana Panamkarana. Berbeda dengan pendahulunya, Rakai Panangkaran memiliki ketertarikan yang besar pada agama Buddha. Ia dikenal sebagai raja yang membangun Candi Kalasan, sebuah tempat ibadah yang didedikasikan untuk Buddha Tara.

Raja Rakai Panangkaran membangun Candi Kalasan, sebuah candi Buddhis yang didedikasikan untuk Buddha Tara. Seorang raja Buddhis, dikatakan bahwa Rakai Panangkaran turun tahta untuk menapak jalan spiritual.
Pada masa pemerintahannya, Rakai Panangkaran membangun banyak candi selain Candi Kalasan, seperti Candi Sari dan Candi Lumbung. Ia juga diyakini telah memprakarsai pembangunan Candi Sewu dan wihara Abhayagiri.
Sebuah prasasti Abhayagiri bertajuk 792 M menyebutkan bahwa Rakai Panangkaran turun tahta untuk menemukan kedamaian spiritual dan berkonsentrasi pada religi. Rakai Panangkaran meninggal sebelum Candi Sewu selesai dibangun.
Beberapa sejarawan telah mengembangkan teori untuk menjelaskan bagaimana Raja Saiwa Sri Sanjaya digantikan oleh seorang raja Buddhis, Rakai Panangkaran.
Teori #1
oleh Van Naerssen, Bosch dan Cœdès
Didukung oleh sejarawan Van Naerssen, F.D.K. Bosch dan George Cœdès, teori ini mengklaim bahwa Rakai Panangkaran adalah putra Raja Sri Sanjaya. Namun, pada masa pemerintahannya, Dinasti Sanjaya dikalahkan oleh Dinasti Shailendra, dan Rakai Panangkaran harus membangun Candi Kalasan di bawah instruksi penguasa Shailendra, Raja Dharanindra.
Teori #2
oleh Profesor Poerbatjaraka, Pusponegoro dan Notosutanto
Para sejarawan Prof. Poerbatjaraka, Marwati Pusponegoro, dan Nugroho Notosutanto mendukung teori kedua, yang menyatakan bahwa Dinasti Sanjaya tidak pernah ada. Mereka percaya bahwa Raja Sri Sanjaya dan Raja Rakai Panangkaran berasal dari Dinasti Shailendra, dan Dinasti Sanjaya tidak ada. Dalam lingkup teori ini, Raja Sri Sanjaya meminta putranya Rahyang Panaraban untuk memeluk agama Buddha. Mereka percaya bahwa Rahyang Panaraban adalah orang yang sama dengan Rakai Panangkaran. Kisah ini didasarkan pada Carita Parahyangan, manuskrip abad ke-16 M.
Teori #3
oleh Slamet Muljana
Sejarawan Slamet Muljana tidak setuju dengan teori pertama bahwa Rakai Panangkaran adalah putra Raja Sri Sanjaya yang dikalahkan oleh Raja Shailendra Dharanindra. Menurut Bpk. Muljana, Rakai Panangkaran tidak mungkin adalah bawahan atau lebih rendah daripada Dharanindra karena ia dipuji sebagai ‘Sailendrawangsatilaka’ (permata Dinasti Shailendra) dalam prasasti Kalasan.
Slamet Muljana mengemukakan teori ketiga, yang mendukung klaim bahwa Rakai Panangkaran bukan putra Raja Sri Sanjaya tetapi seorang raja Buddhis Shailendra yang didaulatnya sendiri. Kesimpulannya didasarkan pada prasasti Mantyasih yang menyatakan Rakai Panangkaran mengambil gelar ‘Sri Maharaja’, gelar yang digunakan oleh raja-raja Shailendra. Menurut teori ini, Rakai Panangkaran adalah seorang raja Buddhis Shailendra yang mengalahkan Dinasti Sanjaya dan naik ke tahta Kerajaan Medang.
Dharanindra, Penakluk Musuh yang Gagah Berani
(memerintah antara 775 – 800 CE)

Ilustrasi seorang seniman menggambarkan Raja Dharanindra
Raja Dharanindra, yang juga dikenal sebagai Raja Indra, adalah penguasa Kerajaan Medang dan sekitarnya. Ia adalah ahli strategi berbakat dalam menjalankan kampanye militer yang sukses. Selama masa pemerintahannya, ia berhasil memperluas kerajaannya hingga mencakup Semenanjung Melayu dan Indocina. Ia dihormati oleh orang-orang dan musuh-musuhnya.
Menurut prasasti Kelurak, Raja Indra juga dikenal sebagai Wairiwarawiramardana atau “Penakluk Musuh yang Gagah Berani”. Sebuah prasasti yang ditemukan di Thailand Selatan juga menyebutkannya, di mana ia disebut sebagai Sarwwarimadawimathana. Prasasti tersebut menggambarkan Raja Dharanindra sebagai emanasi Dewa Hindu Wisnu.
Raja Dharanindra berhasil menaklukkan Ligor dan Kamboja Selatan di Delta Mekong. Ia juga meluncurkan serangan terhadap Champa di tempat yang sekarang disebut Vietnam Selatan.

Candi Sewu, juga dikenal sebagai Manjushrigrha (Rumah Manjushri)
Mengikuti warisan pendahulunya Rakai Panangkaran, Raja Dharanindra juga dikenal sebagai pembangun yang hebat. Dia adalah raja Shailendra yang membangun Candi Sewu, yang juga dikenal sebagai Manjushrigrha (Rumah Manjushri). Prasasti Karangtengah, bertajuk tahun 824 M, menyebutkan bahwa Raja Dharanindra juga bertanggung jawab atas pembangunan Venuvana, dan perencanaan Candi Borobudur dan Candi Pawon. Saat ini, Candi Sewu dan Borobudur adalah candi Buddhis terbesar kedua dan terbesar di Indonesia.
Peran Raja Dharanindra dalam pembangunan Candi Sewu dijelaskan dalam prasasti Kelurak bertajuk tahun 782 M. Prasasti Kelurak ditulis dalam bahasa Sanskerta dengan aksara Pranagari. Prasasti itu ditemukan di Pura Lumbung, Desa Kelurak di Jawa Tengah. Saat ini, prasasti tersebut disimpan di Museum Nasional Indonesia, dengan nomor inventaris D.44.
Samaratungga, Pemersatu Kerajaan
(memerintah antara 812 – 833 M)
Samaratungga adalah keturunan Raja Dharanindra, dan ia disebutkan dalam prasasti Karangtengah tanggal 824 Masehi. Semasa hidupnya, Samaratungga mendekatkan relasi antara Kerajaan Medang dan Kerajaan Sriwijaya dengan menikahi Dewi Tara, putri penguasa Sriwijaya, Raja Dharmasetu. Samaratungga kemudian menjadi penguasa tertinggi Kerajaan Sriwijaya dan Medang.

Candi Borobudur yang megah selesai dibangun pada masa pemerintahan Raja Shailendra Samaratungga.
Selama pemerintahannya, Samaratungga menyaksikan penyelesaian candi Buddhis yang megah, yaitu Borobudur. Namun, Samaratungga juga kehilangan daerah yang telah ditaklukkan oleh pendahulunya, Raja Dharanindra. Ia menunjuk Jayavarman II sebagai gubernur Indrapura di Delta Mekong. Sayangnya, Jayavarman II membatalkan aliansi dan mengkhianati kepercayaan Samaratungga. Ia menaklukkan area Delta Mekong dan mendirikan Kerajaan Khmer.
Samaratungga dan Dewi Tara memiliki dua anak yang terkenal, putranya Balaputradewa dan putrinya Pramodhawardhani yang menikahi Rakai Pikatan, seorang anggota Dinasti Sanjaya.
Pembangunan Candi Borobudur
Informasi Tambahan Tentang Prasasti Karangtengah
Prasasti Karangtengah terdiri dari lima keping batu bertajuk tahun 824 M. Prasasti batu itu ditemukan di Dusun Karangtengah di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Prasasti Karangtengah ditulis dalam dua bahasa: Jawa Kuna dan Sanskerta.
Prasasti Karangtengah menyebutkan Raja Samaratungga dan putrinya, Pramodhawardhani, yang mendirikan sebuah bangunan suci bernama Jinalaya. Prasasti itu juga menyebutkan bangunan Buddhis lain bernama Venuvana yang berarti ‘Hutan Bambu’ dalam bahasa Sanskerta, dan di situlah abu ‘Raja Awan Mega’ dimakamkan. Ada kemungkinan bahwa Raja Awan Mega merujuk pada Raja Dharanindra. Beberapa sejarawan telah mengidentifikasi Jinalaya sebagai Borobudur, sementara Venuvana adalah Candi Mendut atau Ngawen.
Prasasti Karangtengah juga menggambarkan seorang raja bernama ‘Rakai Patapan pu Palar’ yang memutuskan dalam dekrit kerajaannya bahwa sawah ladang di Kayumwungan dibebaskan dari pajak pada tahun 824 Masehi. Rakai Patapan pu Palar mengacu pada Rakai Garung. Sementara sejarawan Slamet Muljana menyarankan bahwa Rakai Garung adalah nama lain untuk Samaratungga, dan yang lain berpendapat bahwa Rakai Garung mungkin adalah bupati yang memaksakan bimbingannya pada putra Samaratungga, yaitu Balaputradewa, yang naik tahta sebagai putra mahkota setelah ayahnya meninggal.
Pramodhawardhani, Rakai Pikatan dan Balaputradewa
Kedamaian Kerajaan Medang di bawah pemerintahan Shailendra segera terhempas ke dalam kekacauan disebabkan perang saudara yang terjadi setelah Samaratungga meninggal. Di satu sisi adalah putrinya Pramodhawardhani dan suaminya Rakai Pikatan; lalu di sisi yang bersebrangan adalah putranya Balaputradewa.

Candi Plaosan dibangun oleh Rakai Pikatan, umat Hindu pemuja Siwa, untuk istrinya yang beragama Buddha, Pramodhawardhani, putri dari Dinasti Shailendra.
Pramodhawardhani menikahi Rakai Pikatan, seorang pangeran Hindu dari Dinasti Sanjaya. Setelah ayahnya meninggal, saudara laki-lakinya, Balaputradewa, menjadi penguasa yang sah dari Kerajaan Medang dan Sriwijaya. Namun, Balaputradewa terlibat dalam konflik dengan Rakai Pikatan, dan ini berkembang menjadi perang saudara. Rakai Pikatan mengalahkan Balaputradewa dan merebut tahta Kerajaan Medang. Balaputradewa harus mundur ke Kerajaan Sriwijaya di mana ia menjadi penguasa.
Setelah kekalahan Balaputradewa, Rakai Pikatan dan Pramodhawardhani secara aktif membangun candi Hindu dan Buddhis yang berdekatan satu sama lain. Candi Hindu Prambanan, Candi Buddhis Plaosan, dan Candi Buddhis Sajiwan semuanya dibangun pada masa ini, yang menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan mereka, terjadi keharmonisan antara agama Hindu dan Buddha.
Pramodhawardhani dan Rakai Pikatan
(memerintah antara 840-an – 856 M)
Pramodhawardhani adalah putri Samaratungga. Ia juga dikenal sebagai Sri/Cri Sanjiwana, Sri/Cri Kahulunan dan Nini Haji Rakryan Sanjiwana. Pramodhawardhani disebutkan dalam beberapa prasasti batu seperti Karangtengah, Tri Tepusan dan Rukam. Ia terkenal akan kecantikannya dan dikisahkan bahwa gambar dewi Durga di Candi Prambanan dibuat serupa dengannya.
Sebagai insan yang sangat spiritual, Pramodhawardhani menyediakan tanah bebas pajak untuk mendanai dan memelihara Bhumisambhara (Candi Borobudur), menurut prasasti Tri Tepusan bertajuk 842 M. Prasasti Rukam yang bertajuk tahun 907 M menyebutkan Desa Rukam, yang sebelumnya dihancurkan oleh letusan gunung berapi. Desa itu kemudian dipulihkan dan Pramodhawardhani meresmikan pemukiman yang baru saja direstorasi. Prasasti Rukam juga menyebutkan bahwa penduduk Desa Rukam memiliki kewajiban untuk memelihara bangunan suci di Limwung. Bangunan sakral ini telah diidentifikasi sebagai Candi Sojiwan di masa kini.
Pertunangan Pramodhawardhani dengan Pangeran Saiwa dari Sanjaya, Rakai Pikatan, dipandang sebagai rekonsiliasi politik antara Dinasti Hindu Sanjaya dan Dinasti Buddhis Shailendra. Aliansi antaragama ini dicatat dalam prasasti Shivargrha. Prasasti Shivargrha, juga dieja sebagai Shivargha, bertajuk tahun 856 M, masa setelah akhir pemerintahan Rakai Pikatan. Saat ini, prasasti Shivargrha disimpan di Museum Nasional Indonesia, Jakarta dengan nomor identifikasi D.28.
Prasasti Shivargrha juga menyebutkan bahwa berbeda dengan permaisuri Pramodhawardhani yang Buddhis, Raja Rakai Pikatan sendiri adalah seorang Hindu yang menyembah Siwa. Namun demikian, ia tetap membangun Candi Plaosan sebagai pengabdian kepada istrinya yang beragama Buddha.
Dalam prasasti Shivargrha, digambarkan Rumah Siwa (Shivargrha), yang merujuk ke Candi Prambanan, serta proyek modifikasi Sungai Opak dekat Prambanan. Prasasti ini juga merujuk pada pertempuran suksesi kerajaan di Kerajaan Medang antara Balaputradewa dan Rakai Pikatan.
Balaputradewa, Sponsor Nalanda
(memerintah antara 860 -? M)

Ilustrasi seorang seniman menggambarkan Raja Balaputradewa
Menurut beberapa sumber, Balaputradewa adalah putra bungsu dan pewaris Raja Samaratungga dan istrinya Dewi Tara. Sumber lain mengatakan bahwa Balaputradewa sebenarnya adalah adik dari Raja Samaratungga, dan bukan putranya. Teori sebelumnya lebih populer, menjadikan Balaputradewa sebagai pangeran Shailendra yang turun dari garis bangsawan Kerajaan Medang yang terkenal (pihak ayah) dan Kerajaan Sriwijaya (pihak ibu).
Ayah Balaputradewa, Raja Samaratungga, meninggal ketika ia masih kecil. Sebagai pewaris tahta yang masih muda, otoritas Balaputradewa di Jawa Tengah seringkali ditantang oleh para bangsawan setempat; ia bahkan dipaksa menerima bimbingan seorang pria bernama Rakai Garung, seorang anggota Dinasti Sanjaya yang menjadi kerabat Balaputradewa melalui pernikahan putranya, Rakai Pikatan dengan Pramodhawardhani, saudara perempuan Balaputradewa. Hingga pemerintahan Rakai Garung berakhir pada tahun 832 M ditandai dengan menghilangnya dirinya, maka pemerintahan Raja Balaputradewa di Jawa Tengah tetap relatif damai.
Namun akhirnya, keberadaan Shailendra di Jawa menemui ujungnya. Catatan sejarah sebelum prasasti Karangtengah 824 M menunjukkan bahwa Dinasti Shailendra hidup berdampingan dengan damai dengan Dinasti Sanjaya hingga pertengahan abad ke-9 M. Saat itu sekitar tahun 852 M, saudara ipar Balaputradewa yaitu Rakai Pikatan mulai menggalang dukungan para bangsawan setempat, dan Balaputradewa yang khawatir mencoba menekannya. Namun usahanya gagal total karena pengalamannya yang kurang dan akhirnya, Rakai Pikatan mengalahkan saudara iparnya.
Jawa kemudian jatuh ke tangan Dinasti Sanjaya, yang kemudian mendirikan Kerajaan Medang yang bertahan hingga abad ke-11 M, ketika Dinasti Sriwijaya menegaskan kembali dominasi mereka atas Jawa. Namun hingga saat itu, keberadaan Shailendra di Jawa secara efektif berakhir dengan kekalahan Balaputradewa, yang tercatat dalam prasasti Shivargrha. Mereka terpaksa meninggalkan Jawa pergi ke Sumatra, yang merupakan kursi dari Dinasti Sriwijaya dan rumah ibu Balaputradewa, Dewi Tara. Di sana, Balaputradewa menjadi penguasa tertinggi Kerajaan Sriwijaya.

Prasasti Nalanda (sekitar 860 M) ditemukan di India.
Sampai tahun 860 Masehi, Shailendra tidak lagi muncul dan prasasti Jawa manapun tidak menyebutkannya. Baru pada 860 Masehi nama mereka muncul kembali, kali ini di India dan di prasasti Nalanda. Prasasti Nalanda ditemukan di ruang depan Biara 1 di kompleks Biara Nalanda pada tahun 1921. Dalam prasasti yang terukir pada pelat tembaga ini, Balaputradewa dicatat sebagai Raja Suvarṇadvipa (Sumatra modern). Pelat ini mencatat pemberian dari Raja Shailendra Balaputradewa yang, karena “tertarik oleh berbagai keunggulan Nalanda”, telah membangun sebuah biara di sana.
Disebutkan bahwa Balaputradewa mengirim seorang duta besar ke Devapaladeva, Raja Bengala, memintanya untuk memberikan pendapatan dari lima desa untuk pembangunan dan pemeliharaan biara. Devapaladeva, sponsor setia Buddhisme, mengabulkan permintaannya. Bahkan, dikatakan bahwa Devapaladeva juga menyetujui pembangunan banyak kuil dan biara di Magadha, mempertahankan biara di Uddandapura (Odantapuri) dan melindungi Universitas Vikramshila. Tulisan itu berbunyi:
“Kami diminta oleh Maharaja Balaputradewa yang termasyhur, raja Suwarnadwipa melalui seorang utusan yang saya perintahkan, untuk membangun sebuah biara di Nalanda seiring dengan dekrit penganugrahan penghasilan untuk Buddha Bhagawan, berdiamnya semua kebajikan utama seperti Prajnaparamita; untuk persembahan, persembahan, tempat berlindung, pakaian, sedekah, tempat tidur, kebutuhan orang sakit seperti obat-obatan, dll dari Sangha para bhiksu yang terhormat dari empat penjuru, para Bodhisattva yang fasih dalam tantra, dan delapan tokoh suci agung (yaitu aryapudgalas); untuk proses penulisan dharma-ratna sutra-sutra Buddhis dan untuk pemeliharaan serta perbaikan biara (ketika) rusak.
Ada seorang raja Yavabhumi (Yava atau Jawa), yang dimuliakan dari Dinasti Sailendra, yang kaki teratainya bermekaran oleh kilauan permata di barisan mahkota yang bergetar di kepala banyak pangeran, dan namanya sungguh sesuai yaitu penakluk musuh yang pemberani (vira-vairi-mathana). Kemasyhurannya terjadi saat menginjakkan kakinya di wilayah istana (putih), di bunga lili air putih, di tanaman teratai, keong, bulan, melati dan salju dan dinyanyikan tanpa henti di semua penjuru, meliputi seluruh alam semesta. Pada saat raja mengerutkan kening dalam kemarahan, takdir musuh juga hancur bersamaan dengan hati mereka.”
Candi Terkait Dinasti Shailendra
Dinasti Shailendra adalah pembangun candi yang makmur dan penyebar agama Buddha yang berkuasa. Selama masa pemerintahan mereka, mereka membangun banyak candi Buddhis, banyak di antaranya masih berdiri hingga hari ini.
Gaya Arsitektur
Dinasti Shailendra membuat serangkaian monumen yang luar biasa, termasuk salah satunya adalah candi terbesar sepanjang masa yaitu Candi Borobudur yang terkenal di dunia. Dari miniatur stupa Borobudur yang berongga-rongga hingga candi kembar Plaosan, rupang-rupang dari Dinasti Shailendra mengadopsi bentuk dan gaya Jawa Tengah mereka yang khas meskipun asal muasalnya berasal dari seni India.

Borobudur, contoh arsitektur terkenal di dunia dari Dinasti Shailendra
Mayoritas kompleks candi dan bangunan besar di Jawa Tengah bersifat Buddhis dan Shailendra berperan atas banyak monumen di sana, seperti Mendut, Pawon, Kalasan, Sewu dan banyak lagi.
Menganalisa dari gayanya, dipetakan ada dua periode pembangunan candi Buddhis selama masa Dinasti Shailendra. Yang pertama adalah pada masa Rakai Panangkaran, dan yang lain pada periode setelahnya, selama masa pemerintahan Raja Samaratungga.
Di masa awal, candi yang dibangun adalah Borobudur, Kalasan, Lumbung, Mendut, Pawon, Sari dan Sewu, sedangkan Plaosan dan Ngawen dibangun pada periode setelahnya.
Seperti yang diilustrasikan dalam The Buddhist temples of the Śailendra Dynasty in Central Java oleh Marijke I. Klokke, ada beberapa perbedaan yang jelas antara arsitektur di kedua periode tersebut. Misalnya, kepala monster di periode awal tidak memiliki rahang bawah dan kaki yang menghadap ke bawah. Di masa awal, struktur bangunan Buddhis yang besar dan candi-candi Hindu kecil ada di daerah pinggiran sedangkan pada masa setelahnya, candi-candi Hindu yang lebih besar dibangun dengan gaya ornamen yang lebih seragam di wilayah yang luas.

(Atas) Kepala monster periode awal
(Bawah) Kepala monster periode berikutnya
Pada masa sebelumnya, ornamen antefiks (blok vertikal yang berada di ujung ubin penutup dari atap) profilnya tidak teratur dan mengikuti ornamen pada permukaan yang menghadap ke luar. Sebaliknya, antefiks pada masa selanjutnya memiliki profil yang jelas. Ornamen yang bertalian di masa awal mengulang bentuk-bentuk geometris sementara hiasan-hiasan pada masa berikutnya muncul dalam bentuk bunga dengan empat kelopak, di samping bentuk-bentuk geometris. Motif daun, seperti daun berjari enam atau gulungan daun juga disertakan.
Studi ornamen Jawa Tengah menunjukkan bahwa gaya dan desainnya sudah sangat terlokalisasi, meskipun desainnya berasal dari India. Satu kesamaan adalah ornamen yang bertalian, misalnya, yang terdiri dari bujur sangkar dan lingkaran, ditemukan di Candi Banyunibo yang serupa dengan yang ada pada stupa nazar di Bodhgaya.
Pertukaran budaya, terutama kontak dengan Sri Lanka dan barang-barang dagang yang masuk ke Indonesia selama periode Tang, juga mempengaruhi seni Jawa Tengah selama periode Shailendra. Misalnya, sutra Tiongkok, yang diperkecil menurut ukurannya, digambarkan di bangunan utama kompleks Candi Sewu. Ada juga orang bijak berpenampilan Tionghoa di Sewu dan Merak.
Tiga Candi Mendut, Pawon dan Borobudur
Menurut Profesor Lokesh Chandra, Shailendra membangun candi-candi seperti Mendut dan Borobudur sebagai “kesepakatan yang penuh atas stabilisasi kedaulatan cakravartin dari Sailendra”. Serangkaian tiga candi – Mendut, Pawon dan Borobudur – disebutkan sebagai saling berhubungan. Terletak di garis lurus dari utara ke selatan, ketiga candi ini menunjukkan desain rupang yang serupa di badan candi.
Prof. Chandra menyatakan bahwa Mendut dan Pawon terkait dengan kelas carya-tantra. Konstruksi mereka sesuai dengan informasi dalam teks tantra Indonesia, Sang Hyan Kamahayanan Mantranaya, yang mencakup syair ajaran yang diturunkan dari Mahavairocana-sutra dan Adhyardha-satika Prajnaparamita. Sutra Mahavairocana juga disebut sebagai Garbhadhatu mandala dalam tradisi Tiongkok-Jepang, dan istadewata utama dari tantra ini adalah Abhisambhodi Vairochana (bahasa Jepang: Garbhadhatu Vairochana).
Ketika merujuk ke Candi Mendut, Raja Dharanindra disebutkan telah menggunakan istilah teknis, carya-tantra Tathagata-kula. Tathagata-kula memiliki dua komponen, Mahavairocana-abhisambodhi-tantra dan Acala-kalpa, dan keduanya menunjukkan hubungan antara Candi Mendut dan Candi Pawon.

Setiap tahun, ribuan umat Buddhis berjalan dari Candi Mendut ke Candi Borobudur, melewati Candi Pawon sebagai bagian dari prosesi Hari Waisak untuk memperingati kelahiran, pencerahan, dan wafatnya Buddha Shakyamuni. Klik untuk memperbesar.
Candi Mendut terkait dengan tantra Mahavairocan-abhisambodhi, sedangkan Kuil Pawon terkait dengan Acala-kalpa. Oleh karena itu, Pawon lebih dekat ke Mendut karena kedua candi dikatakan berhubungan, sementara Borobudur yang termasuk dalam yoga-tantra lebih jauh. Jarak antara Pawon dan Mendut adalah 1.150 meter, sedangkan jarak antara Pawon dan Borobudur adalah 1.750 meter – satu setengah kali jarak antara Pawon dan Mendut.
Dalam tradisi Tibet, tantra Mahavairocana segera disusul oleh Acala-kalpa di Kangyur. Karena Kangyur Tibet disusun secara sistematis, dengan urutannya ditentukan oleh keterkaitan antara perkembangan doktrinal, ritual dan filosofis, penempatan Mahavairocana-sutra dan Acala-kalpa di dalam Kangyur bukanlah suatu kebetulan. Sebaliknya, hal ini terjadi untuk menunjukkan hubungan yang dekat dan integral di antara mereka.
Oleh karena itu, jarak yang lebih dekat antara Pawon dan Mendut, serta jarak yang lebih jauh antara Pawon dan Borobudur merupakan indikasi bahwa candi-candi ini direncanakan sesuai dengan norma-norma naskah carya-tantra dan yoga-tantra.
Di era kontemporer, saat bulan purnama di bulan Mei atau Juni, umat Buddhis di Indonesia merayakan upacara Waisak tahunan dengan berjalan kaki (berpradaksina) dari Mendut, melewati Pawon, dan berhenti di Borobudur.
Candi Mendut
Lokasi
Candi Mendut ditemukan di Desa Mendut, Kecamatan Mungkid di Magelang, Jawa Tengah. Berjarak tiga kilometer dari Candi Borobudur. Menurut De Casparis (1950), Mendut adalah “satu kesatuan kompleks dengan Pawon dan Borobudur” dan yang tertua dari antara ketiga candi tersebut.
Sejarah
Mendut dibangun oleh raja Dinasti Shailendra, yang diidentifikasi sebagai Samaratungga atau Dharanindra. Asal pastinya tidak jelas; beberapa mengatakan bahwa berdasarkan prasasti Karangtengah tahun 824 M, Samaratungga yang membangun Mendut, sementara sejarawan lainnya menganggapnya sebagai Dharanindra.
Arsitektur
Mendut berbentuk persegi panjang dan tinggi 26,4 meter. Berada di landasan setinggi dua meter dan memiliki 31 panel relief di sekelilingnya, dengan saluran untuk mengalirkan air dari jalan setapak.
Di dalam Candi Mendut, ada “Panca Tathagata” dari Buddhisme Vajrayana, dengan Buddha Wairocana sebagai istadewata utama, diapit oleh Avalokiteswara dan Bajrapani. Empat patung Buddha lainnya sudah tidak ada lagi, menyisakan empat relung kosong.
Di dinding di luar, delapan bodhisattwa berada di sudut, dengan Prajnaparamita di dinding kanan, Akasagarbha di dinding kiri, dan Lokeswara di dinding belakang.
Candi Pawon
Lokasi
Candi Pawon terletak di Desa Borobudur di Magelang, Jawa Tengah pada garis lurus yang membentang antara Mendut dan Borobudur. Juga dikenal sebagai Candi Bajranalan, Candi Pawon berjarak dua kilometer ke arah timur laut Candi Borobudur, dan satu kilometer di sebelah tenggara Candi Mendut.
Sejarah
Pawon berarti ‘dapur’ dalam bahasa Jawa, yang berasal dari kata dasar ‘awu’ (artinya ‘debu’). Pawon, dari kata ‘Per-awu-an’ (“tempat yang berisi abu”) yang juga dapat berarti sebuah candi penyimpanan abu raja yang dikremasi.
Nama lain Pawon, Bajranalan, berasal dari kata-kata Sanskerta ‘vajra’ (artinya ‘petir’ atau mengacu pada alat upacara Buddha) dan ‘anala’ (artinya ‘api’ atau ‘api’). Di Bali, diketemukan teks yang menggambarkan Vajranala, yang disebutkan duduk dalam kobaran api, murni seperti bulan musim gugur, dengan tiga mata dan empat lengan memegang tongkat, abhaya mudra, tasbih mala dan vas.
Api sebagai bagian dari nama alternatif Pawon sesuai dengan bangunan Pawon yang sebenarnya yang mana jendela-jendela kecil dibangun untuk mengeluarkan asap ketika upacara api pemurnian yang disebut ‘homa’ (atau ‘goma’). Ritual homa berasal dari ritual Weda, tetapi memuja para istadewata Buddhis dan dilakukan oleh para rohaniwan Buddhis.
Istadewata utama yang diseru dalam beberapa tradisi homa, seperti yang ada di Jepang, adalah Acalanatha (Fudo Myoo 不動明王). Dalam Empat Ritus Mudra untuk upacara homa (konsekrasi api) dari Jepang, keempatnya adalah:
- Ritus pendahuluan 18 Langkah
- Vajradhatu
- Garbhadhatu
- Homa atau Fudo (Acala)
Acala di Jepang selalu dilukiskan dengan nyala api dan segala perlambangannya, yang bersesuaian dengan keberadaannya sebagai Vajra-jval-anal-arka (Vajranala).
Dalam Chu Fo Pú-sa Sheng Hsiang Tsan, yang ditulis Changkya Rolpai Dorje, Jvalanala (bahasa Tibet: me-ltha-hbar-ba) dianggap sebagai manifestasi dari Acala. Oleh karena itu, Candi Pawon pastilah merupakan kuil homa dengan Acala sebagai istadewata utama.
Arsitektur
Kuil Pawon didirikan pada landasan persegi panjang yang naik 1,5 meter dari tanah. Ada landasan 20-sudut di tepi permukaan dasar sementara sisi landasan dihiasi dengan rupang yang menggambarkan bunga dan tanaman merambat menempel. Beberapa pengamat telah mencatat bahwa Candi Pawon lebih menyerupai candi Hindu daripada candi Buddhis lainnya, terutama karena tubuh Candi Pawon ramping.
Candi Borobudur
Lokasi
Borobudur adalah candi Buddhis terbesar di dunia dan terletak di kota Muntilan, Jawa Tengah. Berada sekitar 42 kilometer barat laut Yogyakarta, kompleks candi ini dibangun di antara dua gunung berapi kembar, Sundoro-Sumbing dan Merbabu-Merapi, dan dua sungai, Progo dan Elo.
Sejarah
Dikisahkan membutuhkan waktu 75 tahun untuk membangun dan menyelesaikannya pada masa Raja Samaratungga, secara misterius Borobudur kemudian ditinggalkan karena perhatian tergeser ke Timur, dan juga terjadinya konversi Jawa ke Islam. Penemuan kompleksnya adalah berkat Sir Thomas Stamford Raffles pada tahun 1814. Raffles menindaklanjutinya dengan merujuk pada Hermann Cornelius, insinyur Belanda yang ia kirim untuk menggali situs tersebut. Untuk mengungkap monumen ini, Cornelius dan 200 anak buahnya menebang pohon, membakar tumbuhan dan menggali tanah.
Seluruh kompleks sepenuhnya digali pada tahun 1835 dan sejak itu banyak pekerjaan restorasi dan pelestarian yang telah dilakukan, termasuk yang didanai oleh pemerintah Hindia Belanda, serta pemerintah Indonesia dan UNESCO. Kompleks candi ini terdaftar sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO pada tahun 1991.
Situs suci ini disebutkan dalam dua prasasti. Menurut prasasti Karangtengah bertajuk tahun 824 M, bangunan ini disebut sebagai Jinalaya, “alam bagi mereka yang telah menaklukkan hasrat duniawi dan merealisasi pencerahan”, yang diresmikan oleh Pramodhawardhani, putri Raja Samaratungga. Ia juga diidentifikasi sebagai Bhūmi Sambhāra Bhudhāra, “gunung kebajikan gabungan dari sepuluh tingkat Bodhisattwahood”, dalam prasasti Tri Tepusan bertajuk 842 M.
Arsitektur
Borobudur adalah sebuah keajaiban arsitektur. Sang arsitek, Gunadharma, yang “… membawa tongkat pengukur, mengetahui berbagai penggolongan ketika menilik dirinya terdiri dari bagian-bagian”, dikatakan telah memanjat Gunung Menoreh dan memerintahkan para pembangunnya untuk menyelaraskan konstruksi dengan bintang ‘utara sejati’. Relief sebuah kapal di sebelah timur Borobudur menunjukkan sebuah sampan cadik ganda berlayar di bawah benda-benda langit. Pada zaman dahulu, orang Indonesia dikisahkan telah dapat mengarungi samudra semata-mata berdasarkan posisi bintang-bintang.
Butuh sekitar 55.000 meter kubik batu andesit yang dipotong sesuai ukurannya, yang nantinya diangkut ke situs dan diletakkan tanpa mortar untuk membangun monumen ini, dengan sistem drainase berupa 100 moncong berbentuk raksasa atau Makara di setiap sudut.
Kompleks Borobudur merupakan kombinasi dari stupa (struktur hemisfer Buddhis yang dibangun sebagai rumah relik), dengan candi di pegunungan dan mandala Tantra Buddhis, yang merupakan simbol spiritual dan ritual yang mewakili alam semesta, kosmologi Buddhis, dan hakekat batin. Kompleks ini memiliki salah satu perpaduan relief Buddha terbesar dan terlengkap di dunia, dengan 2.672 panel relief dan 504 patung Buddha. 72 patung Buddha, duduk di dalam stupa berlubang yang mengelilingi kubah stupa pusat.
Pondasinya berukuran sekitar 118 meter di setiap sisinya dengan sembilan landasan. Rute dimulai dari dasar monumen, lalu naik ke atas melewati tiga tingkat alam di kosmologi Buddhis:
- Kāmadhātu (alam nafsu keinginan) diwakili oleh pondasi landasan.
- Rupadhatu (alam bentuk) diwakili oleh lima landasan persegi, dan
- Arupadhatu (alam tanpa bentuk) diwakili oleh tiga landasan melingkar yang polos.
Peziarah harus melewati tangga dan koridor dengan 1.460 panel relief naratif di dinding dan langkan. ‘Perjalanan’ ini mirip dengan jalan menuju pembebasan, di mana para makhluk memulai dari tingkat terendah di alam nafsu (kamaloka). Dengan realisasi dan kemajuan spiritual, seseorang bergerak ke alam bentuk (rupaloka) dan, kemudian, ke alam tanpa bentuk (arupaloka).
Tingkat pertama Borobudur, menunjukkan relief yang menggambarkan Mahakarmawibhanga (Sutra Klasifikasi Karma yang Agung) dan Lalitawistara (Sutra Sandiwara Spiritual), menunjukkan cara untuk menemukan penggugahan pribadi dari samsara.
Penggambaran ini diikuti oleh relief-relief yang menggambarkan Gandhavyuha (Jalan Masuk ke Realita Keberadaan) dan Bhadracari (Ikrar Samantabhadra untuk tidak masuk ke dalam nirwana tetapi bertindak untuk mengusahakan pencerahan kepada masyarakat). Ajaran ini menunjukkan jalan Mahayana seorang Bodhisattwa. Gandhawyuha, yang menampilkan Sudhana dan guru-gurunya, menunjukkan bahwa segala jenis orang dapat mengajari kita sesuatu jika kita dapat mengenali kualitas spesial mereka. Masing-masing dari gurunya, dengan yang terakhir Samantabhadra, mengajar Sudhana tentang sifat kebijaksanaan dan welas asih dan kemudian mendorongnya untuk melanjutkan perjalanan.
Candi Sewu
Lokasi
Candi Sewu terletak di Desa Bugisan di Kecamatan Prambanan di Klaten, Jawa Tengah. Terletak 17 kilometer dari Kota Yogyakarta, situs ini dianggap satu kompleks dengan Candi Prambanan, meskipun terletak dua kilometer di utara Candi Prambanan.
Sebagai candi Buddhis terbesar kedua di Jawa, Sewu berarti ‘seribu’, meskipun hanya memiliki total 253 bangunan. Nama ‘seribu kuil’ sesuai dengan legenda lokal Roro Jonggrang yang kisahnya terkait dengan asal usul Candi Sewu.
Sebagai balasan atas serangan sebelumnya, tentara Pengging mengepung Boko, negara tetangganya, dan merebut istana. Dalam prosesnya, pemimpin mereka Prabu Boko dibunuh oleh kekuatan gaib Pangeran Bandung Bandawasa. Saat berada di Boko, Pangeran Bandung Bandawasa dari Pengging menjadi terpesona oleh kecantikan Putri Boko Roro Jonggrang.
Sang pangeran melamar, tetapi sang putri yang berkabung menolak tawarannya. Karena Bandung Bandawasa sangat bertekad, sang putri akhirnya mengalah tetapi dengan dua syarat: pertama, sang pangeran harus membangun sebuah sumur bernama Jalatunda dan kedua, ia harus membangun seribu candi dalam satu malam.
Sekali lagi, menggunakan kekuatan gaibnya, sang pangeran memanggil jin untuk memulai konstruksi. Ketika sumur selesai, ia ditipu untuk masuk ke dalam sumur dan dikubur di dalam sumur. Namun, ia berhasil melarikan diri. Sang pangeran kemudian melanjutkan untuk membangun 999 kuil pertama dan mulai mengerjakan yang terakhir. Untuk menghentikannya dari mencapai tujuan, sang putri dan pelayannya menyalakan api di timur dan menumbuk padi dengan marah, berusaha menipu para jin dengan melakukan kegiatan yang biasanya dilakukan saat fajar. Para Jin lalu termakan umpan dan buru-buru melarikan diri kembali ke bumi, meninggalkan candi terakhir yang belum selesai.
Ketika sang pangeran mengetahui tentang hal ini, ia sangat marah oleh penipuan itu dan ia mengutuk Roro Jonggrang, mengubahnya menjadi fitur di candi terakhir, yaitu rupang Durga di ruang kamar utara dari kuil utama Prambanan, yang saat ini masih dikenal sebagai Roro Jonggrang atau Gadis Ramping. 1000 candi yang dibangun adalah bagian dari kompleks Candi Sewu.
Beberapa mengklaim bahwa legenda tersebut mencerminkan perebutan kekuasaan historis antara Shailendra dan Dinasti Sanjaya untuk menguasai Jawa Tengah yang terjadi di wilayah tersebut selama abad ke-9 M. Raja Prabu Boko dalam legenda itu terinspirasi oleh Raja Samaratungga dari Dinasti Shailendra, Pangeran Bandung Bondowoso adalah Rakai Pikatan, seorang pangeran dari Dinasti Sanjaya, sementara Roro Jonggrang adalah Pramodhawardhani, istri Rakai Pikatan dan putri Raja Samaratungga.
Teori lain yang mungkin lebih populer adalah bahwa legenda itu sesuai dengan perebutan kekuasaan antara Balaputradewa, ahli waris Shailendra, dengan saudara perempuannya Pramodhawardhani. Dibantu suaminya Rakai Pikatan, mereka mengakhiri pemerintahan Shailendra di Jawa Tengah dan Balaputradewa-pun mundur ke Sriwijaya.
Sejarah
Pembangunannya dimulai pada abad ke-8 M pada masa pemerintahan Rakai Panangkaran, dan diselesaikan pada masa Raja Dharanindra dan kemudian diperluas pada masa pemerintahan Rakai Pikatan. Candi Sewu adalah candi Buddhis terbesar di wilayah dataram Prambanan, dibangun sebelum candi Siwaistik Prambanan dan 37 tahun sebelum pembangunan Candi Borobudur yang megah.
Candi ini berfungsi sebagai candi Buddhis kerajaan karena terletak di jantung kota Mataram dan upacara keagamaan untuk kerajaan secara rutin diadakan di candi ini.
Keindahan candi ini dijelaskan dalam prasasti Manjushrigrha (tanggal 792 M). Ada empat candi lain di dekatnya; Candi Bubrah, yang terletak hanya beberapa ratus meter selatan, dan Candi Gana, yang terletak di sebelah timur Candi Sewu, disebutkan sebagai candi pelindung bagi Candi Sewu.
Ada juga reruntuhan Candi Lor di utara Sewu, dan Candi Kulon di sisi barat, yang keduanya sekarang dalam kondisi yang memprihatinkan.
Dua prasasti terkenal, yaitu prasasti Kelurak dan Manjushrigrha, masing-masing berasal dari tahun 782 M dan 792 M, keduanya menunjukkan bahwa kompleks tersebut mungkin disebut sebagai ‘Manjushrigrha’, yang berarti ‘tempat tinggal Manjushri’. Manjushri, yang berarti ‘kemuliaan lembut’, adalah Bodhisattwa kebijaksanaan transenden.
Karena Candi Sewu sangat dekat dengan candi Hindu Prambanan, kemungkinan menunjukkan hubungan yang harmonis antara komunitas Hindu dan Buddhis ketika candi dibangun. Penguasa zaman itu, Rakai Pikatan, adalah seorang pangeran Hindu yang menikahi seorang putri Buddhis dari Dinasti Shailendra, Pramodhawardhani.
Candi itu tertimbun di bawah puing-puing vulkanik dan akhirnya ditemukan kembali pada awal abad ke-19 M, ketika arkeolog Belanda, Hermann Cornelius, menciptakan litograf pertama candi utama Candi Sewu dan Candi Perwara pada tahun 1807. Gambar Candi Sewu juga dimasukkan di buku Sir Thomas Stamford Raffles berjudul The History of Java. Pembersihan dan rekonstruksi candi utama baru dimulai pada tahun 1908 dan hingga hari ini, upaya rekonstruksi dan restorasi masih terus berlanjut.
Arsitektur
Candi Sewu dibangun di lahan berukuran 185 meter dari utara ke selatan dan 165 meter dari timur ke barat. Pintu masuk utama ada di sebelah timur, meskipun ada pintu masuk di masing-masing dari empat arah mata angin. Anda akan menemukan dua patung Dwarapala di setiap pintu masuk sebagai penjaga gerbang. Kompleks ini terdiri dari 249 bangunan di mandala. 240 candi penjaga, yang dikenal sebagai Candi Perwara yang ukurannya lebih kecil, semuanya dibangun dalam empat baris konsentris persegi panjang. Dua baris di sisi luar terdiri dari 168 candi yang lebih kecil sedangkan dua baris di sisi dalam membentuk 72 candi.
Meskipun mereka menyerupai satu sama lain dalam format bingkai persegi, candi-candi ini tidak menjadi rumah bagi rupang atau orientasi yang sama. Candi pokok berupa poligon dengan 20 sisi berbentuk salib, berdiri di ketinggian 30 meter dan lebar 29 meter. Ada empat bangunan di setiap titik mata angin yang menghadap ke luar, lengkap dengan tangga, pintu masuk, dan kamar. Ada lima kamar di candi pusat; ruangan utama ada di tengah sementara kamar-kamar kecil terletak di masing-masing dari empat arah mata angin.
Candi Kalasan
Lokasi
Terletak di Desa Kalasan di barat Prambanan dan 15 kilometer dari Yogyakarta, candi ini khusus didedikasikan untuk Buddha Tara, di sisi selatan jalan utama antara Yogyakarta dan Solo.
Sejarah
Prasasti Kalasan, ditulis dalam bahasa Sanskerta menggunakan aksara Pranagari, yang ditemukan di dekat candi menunjukkan bahwa itu selesai pada tahun Saka 700 Saka atau 778 M.
Arsitektur
Landasan candi berbentuk bak salib Yunani. Tubuh candi penuh hiasan dengan ukiran yang indah dan secara khusus dilapisi dengan getah pohon bajralepa.
Ada sebuah kamar di masing-masing dari empat titik mata angin utama, lengkap dengan tangga dan gerbang. Meskipun tidak ada patung yang ditemukan di dalam candi sekarang, adanya tahta teratai menunjukkan indikasi bahwa kamar-kamar itu pastinya dahulu memiliki rupang Buddha.
Atapnya yang berbentuk segi delapan menampilkan gambar-gambar indah dari para Buddha yang menghadap ke empat titik mata angin, dan setiap gambar Buddha diapit oleh sepasang bodhisattwa sebagai relief.
Candi Plaosan
Lokasi
Satu kilometer di utara Candi Prambanan terdapat Candi Plaosan, sebuah candi unik yang memadukan simbol agama Hindu dan Buddha dalam ukiran candi mereka yang rumit. Candi ini terdiri dari dua kelompok bangunan, Candi Plaosan Utara yang disebut Plaosan Lor dan Candi Plaosan Selatan yang disebut Plaosan Kidul. Kedua kelompok bangunan ini memiliki kesamaan dan karena itu, juga disebut kuil kembar. Mereka dulunya bagian dari gedung yang sama tetapi sayangnya sekarang dipisahkan oleh jalan umum.
Kelompok candi timur laut ini berjarak sekitar tiga kilometer dari Candi Prambanan dan sekitar satu kilometer dari Candi Sewu.
Sejarah
Asal usul candi ini dikaitkan dengan persatuan antaragama yang besar antara dua dinasti yang berkuasa di Jawa Tengah selama abad ke-9 M. Putri Buddhis Pramodhawardhani adalah putri Samaratungga, raja terakhir dari Dinasti Shailendra. Ia menikahi Rakai Pikatan, seorang pangeran dari Dinasti Hindu Sanjaya. Pramodhawardhani menjadi ratu ketika Rakai Pikatan dinobatkan. Beberapa sumber mengatakan bahwa pasangan ini memainkan peran penting dalam pembangunan beberapa candi Hindu dan Budha yang paling megah di Jawa Tengah.
Arsitektur
Candi Plaosan Utara memiliki halaman tengah dengan aula berukuran 21,62 meter kali 19 meter. Pintu masuk ke halaman ada di sebelah barat. Ada tiga altar di bagian timur aula. Di altar timur, anda akan melihat pratima Amitabha, Ratnasambhawa, Wairochana dan Akshobhya. Di altar utara adalah pratima Samantabadhra dan Ksitigarbha, sementara di altar barat adalah gambar Manjushri.
Candi Plaosan Selatan juga memiliki aula di tengah, dikelilingi oleh delapan candi kecil. Anda akan menemukan di sana pratima Tathagata Amitabha, Bajrapani dengan atribut vajra dan Prajnaparamita, yang dianggap “ibu dari semua Buddha”.
Ada relief yang menarik dengan citra pria dan wanita, yang mewakili penyokong kedua biara. Seorang pria duduk bersila dengan tangan dalam gerakan menyembah. Pria lain duduk dikelilingi oleh enam pria yang lebih kecil, dan ia membentuk waradamudra (melambangkan dispensasi anugerah) dengan vas di kakinya. Ada juga rupa seorang wanita yang berdiri dengan buku-buku, palet dan vas di sekelilingnya.
Ada 116 kubah tambahan dan 50 kuil tambahan di kompleks candi ini. Kubah tambahan dan kuil pelengkap terletak di setiap sisi candi utama. Ada juga prasasti yang ditemukan, satu di koin emas di utara candi utama dan satu lagi di atas batu di salah satu candi pelengkap.
Berbeda dari candi-candi lain pada zaman itu, teras Candi Plaosan memiliki permukaan yang halus. Dikatakan bahwa ini disebabkan oleh fungsi candi menjaga sutra-sutra Tripitaka yang dimiliki oleh para bhiksu.
Menurut sebuah teori yang dipaparkan oleh Nicholas Johannes Krom, kepala Masyarakat Arkeologi Belanda awal abad ke-20 M, kedua wihara disponsori oleh para pelindung yang berpengaruh dan dibangun untuk para biarawan pria dan wanita – wihara yang menghadap ke selatan yang menggambarkan sosok laki-laki adalah sebuah biara bagi para bhiksu , sementara bagian utara yang menggambarkan sosok wanita untuk bhiksuni.
Candi Ngawen
Lokasi
Merupakan kompleks candi Buddhis dari abad ke-8 M, Candi Ngawen juga dikenal sebagai Kuil Ngawen, terletak di Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Fitur khusus dari candi ini adalah patung singa yang terletak di sudut candi. Ngawen diketemukan membentuk garis lurus dari barat ke timur, bersama dengan tiga candi terdekat lainnya yaitu Mendut, Pawon dan Borobudur.
Sejarah
Ada diskusi bahwa candi ini adalah kuil Venuvana yang dibangun oleh salah satu raja Shailendra, yang disebutkan dalam prasasti Karangtengah. Kata “Ngawen” berarti bambu, sedangkan “Venuvana” adalah hutan bambu.
Arsitektur

Kinnara adalah sosok makhluk mitologis. Di Asia Tenggara, mereka biasanya digambarkan berpasangan – Kinnara dan Kinnari, pasangan wanitanya. Makhluk setengah manusia, setengah burung yang baik hati ini diyakini berasal dari Himalaya, memantau kesejahteraan manusia di saat kesulitan atau bahaya. Klik untuk memperbesar.
Terletak di antara desa dan sawah, kompleks candi ini terdiri dari lima candi, dengan dua candi utama dan tiga candi perwara (tambahan).
Ruang utama memiliki rupang Buddha Ratnasambhava, meskipun sekarang tanpa kepala karena candi ini menderita insiden penjarahan yang mengerikan. Di setiap sudut candi utama, patung singa berdiri sebagai penjaga sementara landasan candi menampilkan kinnara. Anda juga dapat menemukan relung dengan ukiran gaya Jawa kuno yang menjadi tempat rupang zaman dahulu.
Di dua candi, singa digambarkan dalam posisi berdiri dengan kaki belakang dan kaki depan ditekuk. Di tiga candi yang tersisa, singa digambarkan dalam posisi berdiri dengan kaki belakang dan kaki depan menopang kuil. Singa di Ngawen memiliki ekspresi wajah dan bentuk tubuh yang sama dengan singa di Candi Borobudur, walaupun posisinya berbeda.
Artefak Terkait Dinasti Shailendra
Untuk mengisi candi dan tempat ibadah mereka, Dinasti Shailendra memiliki banyak pengrajin, pematung, pelukis dan pemahat yang membuat patung Buddha dan perlengkapan ritual. Ini hanyalah beberapa artefak luar biasa yang muncul dari hasil penggalian arkeologis.
Sosok Manjushri Perak
Dinasti Shailendra adalah pelindung Buddhisme Mahayana dan memuja Buddha Manjushri sebagai dewa utama mereka. Pembangunan sebuah candi agung bernama Vajrāsana Mañjuśrīgṛha (Rumah Vajra Mañjuśrī) dijelaskan dalam prasasti Kelurak dan Manjushrigrha. Setelah diidentifikasi sebagai Candi yang saat ini bernama Sewu, bangunan ini adalah candi terbesar kedua setelah Borobudur dan dibangun pada abad ke-8 M.
Sosok Manjushri perak ini ditemukan di Ngemplak Semongan, Indonesia. Manjushri menurut tradisi artistik Shailendra digambarkan sebagai pemuda yang tampan. Gaya ini mirip dengan seni Kerajaan Pala di Nalanda, India. Dia duduk dengan kaki kanan ke bawah, ditopang oleh teratai dan kaki kiri ke atas, sementara telapak tangan kanannya terbuka menghadap ke bawah dan tangan kirinya memegang utpala (teratai biru). Ada gambar corak bunga di setiap telapak tangannya dan Ia mengenakan kalung taring harimau.
Timbunan Wonoboyo
Timbunan Wonoboyo mengacu pada artefak emas dan perak dari Kerajaan Medang abad ke-9 M di Jawa Tengah, Indonesia. Ditemukan pada bulan Oktober 1990, di Dusun Plosokuning, Desa Wonoboyo, temuan arkeologis yang signifikan ini mencakup lebih dari 1.000 objek upacara, mulai dari mangkuk emas hingga gelang dan cincin.
Desain yang rumit dengan prasasti menunjukkan kualitas dan pengerjaan pengrajin Jawa selama periode waktu itu. Timbunan ini dianggap sebagai milik raja atau individu berkedudukan tinggi selama masa pemerintahan Raja Balitung (899 – 911 M). Ada kemungkinan bahwa lokasi di mana harta ini ditemukan adalah pertapaan kerajaan, karena ditemukannya mangkuk dana emas di gudang Wonoboyo.

Mangkuk emas dengan ilustrasi panorama dari Ramayana sebagai bagian dari penimbunan Wonoboyo.

Kalung besar berbentuk bulan sabit yang biasa menghiasi gajah kerajaan dalam prosesi. Ada juga gelang kaki besar yang pas dengan kaki gajah.

Entong emas yang digunakan dalam ritual, sesuai dengan tulisan di pinggirnya.
Barang-barang tersebut sekarang ditampilkan di Ruang Harta Karun di Museum Nasional Indonesia, Jakarta dengan replika di Museum Prambanan.
Regalia Emas Suci Jawa
Koleksi 38 ornamen ini adalah salah satu set terlengkap yang ditemukan hingga saat ini, karena setiap keping saling berhubungan satu sama lainnya. Barang-barang yang ditemukan termasuk pita lengan, ikat pinggang atau sabuk, hiasan berbentuk daun, dan lainnya. Hiasan berbentuk daun ini memiliki gulungan cakram teratai gaya India menyerupai yang ditemukan di kompleks Candi Borobudur.
Set ini dapat dibuat untuk rupang-rupang Buddha, atau dikenakan oleh raja atau ratu karena merupakan kebiasaan bagi raja dan ratu untuk mengenakan harta yang diperuntukkan bagi para dewa pada hari-hari khusus. Karena ornamen ini menyerupai yang dikenakan oleh Manjushri, seperti tali dada, sangat mungkin ornamen ini diperuntukkan bagi rupang Manjushri.
Manjushri Batu

Bodhisattva Manjushri dari andesit berasal dari abad ke-9 M ditemukan di Jawa Tengah. Saat ini ditempatkan di Rijksmuseum di Amsterdam, Belanda. (Foto oleh: PHAS / Grup Gambar Universal via Getty Images)
Rupang Manjushri ini terbuat dari andesit, batuan vulkanik yang gelap dan berbutir halus yang merupakan unsur umum lava di beberapa daerah. Tangan rupang yang hilang mungkin pernah membuat pose tangan memutar roda Dharma (dharmachakra mudra) untuk melambangkan permulaan pemutaran ajaran pencerahan Buddha.
Manjushri Perunggu

Ditemukan di Jawa Tengah dan berasal dari paruh kedua abad ke-9 M hingga awal abad ke-10 M. (Sumber: Perunggu Kuno Indonesia: Katalog Pameran di Rijksmuseum Amsterdam dengan Pengantar Umum, oleh Marijke J. Klokke dan Pauline C. M. Lunsingh Scheurleer)
Duduk dalam posisi dhyana-mudra (meditasi), rupang perunggu Buddha Manjushri ini memiliki tali yang melintang di dadanya, sebuah fitur yang dikenal sebagai channawira yang umum dalam perwujudan dewi dan dewa yang berusia di bawah 16 tahun. Fitur lain dari patung ini adalah tiga helai rambut ke atas yang berputar (dikenal sebagai tricira atau sikhandaka), yang merupakan fitur khusus dari gaya memahat Indo-Jawa dan fitur umum pada dewa yang digambarkan dalam rupa anak laki-laki.
Ornamen Tongkat Bhiksu dan Genta

Berasal antara 930 dan 1.500 M. Terbuat dari perunggu dan tingginya sekitar 18,8 cm dan lebar 11,4 cm.
Ornamen mahkota adalah benda yang menandai bagian atas atau akhir suatu objek, dan sering berfungsi sebagai fitur dekoratif atau hiasan. Ornamen ini menghiasi tongkat bhiksu dengan gemerincing cincin, yang sekarang telah hilang, untuk mengisyaratkan kehadirannya, menghimbau orang-orang di sekitarnya untuk memberikan sedekah. Sebuah bola longgar di dalam genta, yang harus berdiri di atas dasar kaki cabang tiga, bergetar setiap kali genta dipindahkan.
Vajrasattva Perak

Terbuat dari perak dengan dasar perunggu, dan tingginya sekitar 13,5 cm, lebar 7,7 cm, dan dalam 6,5 cm.
Vajrasattva (artinya ‘makhluk halilintar’), yang praktiknya sangat baik bagi purifikasi karma, merupakan salah satu dewa Buddhis berkedudukan tinggi. Ia digambarkan di sini dengan duduk di atas tahta teratai, dihiasi dengan pakaian kerajaan. Di tangan kanannya, ia memegang bajra sejajar dada dan di tangan kirinya, ia memegang genta yang terletak di pangkuannya.
Manjushri Perunggu

Berasal dari antara abad ke-9 M dan awal abad ke-10 M. Terbuat dari perunggu dan tingginya sekitar 7 cm, lebar 4 cm, dan kedalaman 5,5 cm.
Manjushri digambarkan di sini ketika duduk di atas tahta teratai dengan kaki terlipat dalam pose padmasana (posisi meditasi lotus penuh). Tangan kanannya membentuk varamudra, diarahkan ke bawah dengan telapak tangannya terbuka, melambangkan pemberian berkah. Tangan kirinya memegang batang utpala (teratai biru), yang berdiri hingga sebahu. Mengenakan rok, ia dihiasi dengan 13 ornamen biasa dari pangkatnya.
Genta

Berasal dari antara 800 dan 900 M. Terbuat dari perunggu, dan tingginya sekitar 18,5 cm dan kedalaman 8 cm.
Bel tangan, atau ghanta, dibunyikan oleh para bhiksu Buddhis selama ritual. Cakram api melingkar dengan salib di tengahnya menggambarkan chakra, roda yang melambangkan ajaran Buddha. Empat wajah Buddha di atas lonceng menghadap ke empat arah mata angin.
Buddha Duduk (dengan tulisan di pangkalan)
Berasal dari abad ke-9 M, patung Buddha duduk perunggu yang indah dan rumit ini ditemukan di Jawa dan tingginya sekitar 9,5 cm.
Museum Balaputradewa
Museum Balaputradewa di Palembang, Sumatra berisi banyak artefak berharga dari Dinasti Shailendra.
Galeri Gambar Berkenaan Dinasti Shailendra
Di bawah ini adalah beberapa karya seni untuk anda nikmati. Semua ini diciptakan oleh pengrajin Dinasti Shailendra, atau oleh seniman yang sejak saat itu telah terinspirasi oleh Dinasti Shailendra termasuk bangunan, monumen dan karya seni yang mereka ciptakan. Dalam beberapa contoh di bawah ini, karya seni ini berusaha menangkap beberapa adegan akan seperti apa kehidupan selama masa kejayaan Dinasti Shailendra.

Sebuah lukisan Borobudur karya Affandi (1907 – 1990), seorang pelukis ekspresionis Indonesia. Klik untuk memperbesar.

Panen Raya Borobudur (atau Grand Harvest Borobudur), sebuah lukisan karya Pardoli Fadli (2009). Klik untuk memperbesar.

Candi Borobudur oleh Splendid Art Prints. Gambar diproduksi sebagai bagian dari buku bergambar anak-anak yang diterbitkan oleh Industrie-Comptoir di Jerman (1790 – 1830). Klik untuk memperbesar.

Sebuah foto tahun 1897 tentang reruntuhan Candi Sewu sebelum pekerjaan restorasi dimulai. Klik untuk memperbesar.

Sebuah tahun 1807 litograf reruntuhan Candi Sewu sedang dibersihkan dan dipulihkan, dibuat oleh arkeolog Belanda Hermann Cornelius. Diberi label salah di sini sebagai ‘Bramin Temple’. Klik untuk memperbesar.

Patung Dewi Durga di Candi Prambanan. Dikatakan bahwa patung Durga ini mirip dengan Pramodhawardhani, permaisuri Rakai Pikatan. Klik untuk memperbesar.

Patung Avalokiteswara berasal dari abad ke-9 M, dari periode Sriwijaya. Itu ditemukan di distrik Chaiya, Thailand.

Arca emas Avalokiteswara dari periode Sriwijaya. Karya seni ini ditemukan di Muarabulian di Jambi, Indonesia. Klik untuk memperbesar.

Patung Wairocana perunggu 34 cm dari periode Sriwijaya, berasal dari abad ke-9 M. Klik untuk memperbesar.
Rekomendasi Bacaan (Unduh Gratis)
Sumber:
- Wikipedia, The Free Encyclopedia, Shailendra Dynasty, February 5, 2019, https://en.wikipedia.org/wiki/Shailendra_dynasty (accessed: 11 May 2019)
- Soedjatmoko, ‘An Introduction to Indonesian Historiography’, Jakarta, Indonesia, Equinox Publishing, 2007.
- ‘Shailendra Dynasty’, Encyclopaedia Britannica, https://www.britannica.com/topic/Shailendra-dynasty, (accessed 20 June 2019).
- ‘Sailendra’, New World Encyclopedia, 2015, http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Sailendra, (accessed 20 June 2019).
- ‘The Sailendra Dynasty: Builders of Borobodur, Agents of Buddhism’, Searching in History, 2015, https://searchinginhistory.blogspot.com/2015/04/the-sailendra-dynasty-builders-of.html, (accessed 20 June 2019).
- ‘Samaragrawira’, Wikipedia: The Free Encyclopedia, 2015, https://en.wikipedia.org/wiki/Samaragrawira, (accessed 20 June 2019).
- ‘Balaputra’, Wikipedia: The Free Encyclopedia, 2019, https://en.wikipedia.org/wiki/Balaputra, (accessed 20 June 2019).
- ‘Dharanindra’, Wikipedia: The Free Encyclopedia, 2019, https://en.wikipedia.org/wiki/Dharanindra, (accessed 20 June 2019).
- ‘Mendut’, Wikipedia: The Free Encyclopedia, 2019, https://en.wikipedia.org/wiki/Mendut, (accessed 20 June 2019).
- ‘Mendut Temple: Witness the Holiest Day of the Buddhist Year in Indonesia’, Wonderful Indonesia, 2019, https://www.indonesia.travel/my/en/destinations/java/yogyakarta/mendut-temple, (accessed 20 June 2019).
- ‘Plaosan Temples’, Lonely Planet, https://www.lonelyplanet.com/indonesia/attractions/plaosan-temples/a/poi-sig/1217643/356546, (accessed 20 June 2019).
- ‘Sewu Temple’, Indonesia-Tourism, http://www.indonesia-tourism.com/yogyakarta/sewu-temple.html, (accessed 20 June 2019).
- Sparavigna, Amelia Carolina Sparavigna, ‘The Sewu Temple and the Zenithal Passage of the Sun, Available from SSRN, (accessed 20 June 2019).
- ‘Sewu’, Wikipedia: The Free Encyclopedia, 2019, https://en.wikipedia.org/wiki/Sewu, (accessed 20 June 2019).
- ‘Sejarah Candi Sewu Singkat dan Legendanya’, SejarahLengkap.com, https://sejarahlengkap.com/agama/buddha/sejarah-candi-sewu, (accessed 20 June 2019).
- ‘Candi Sewu’, Alodia, https://www.alodiatour.com/candi-sewu/, (accessed 20 June 2019).
- ‘Ngawen’, Wikipedia: The Free Encyclopedia, 2019, https://en.wikipedia.org/wiki/Ngawen, (accessed 20 June 2019).
- ‘Ngawen Temple, Magelang’, Indonesia-Tourism, https://www.indonesia-tourism.com/forum/showthread.php?52201-Ngawen-Temple-Magelang, (accessed 20 June 2019).
- andigital, ‘Ngawen Temple’, Temple of Java, http://templeofjava.blogspot.com/2011/01/ngawen-temple.html, (accessed 20 June 2019).
Untuk membaca informasi menarik lainnya:
- Ritus Berlian: Sadhana Harian Dorje Shugden (Bahasa Indonesia)
- Dorje Shugden Gyenze untuk Memperpanjang Umur, Meningkatkan Pahala dan Kekayaan (Bahasa Indonesia)
- Dorje Shugden Trakze Untuk Menghalau Gangguan Ilmu Hitam & Makhluk Halus (Bahasa Indonesia)
- Proyek Pembangunan Stupa Relik Tsem Rinpoche (Bahasa Indonesia)
- ALBUM: Upacara Parinirwana Yang Mulia Kyabje Tsem Rinpoche (Lengkap) (Bahasa Indonesia)
- Parinirwana dari Yang Mulia Kyabje Tsem Rinpoche (Bahasa Indonesia)
- Dinasti Shailendra: Leluhur Buddhisme Mahayana di Indonesia (Bahasa Indonesia)
- Sebuah Doa Singkat Kepada Dorje Shugden (Bahasa Indonesia)
Please support us so that we can continue to bring you more Dharma:
If you are in the United States, please note that your offerings and contributions are tax deductible. ~ the tsemrinpoche.com blog team



























































































































































































































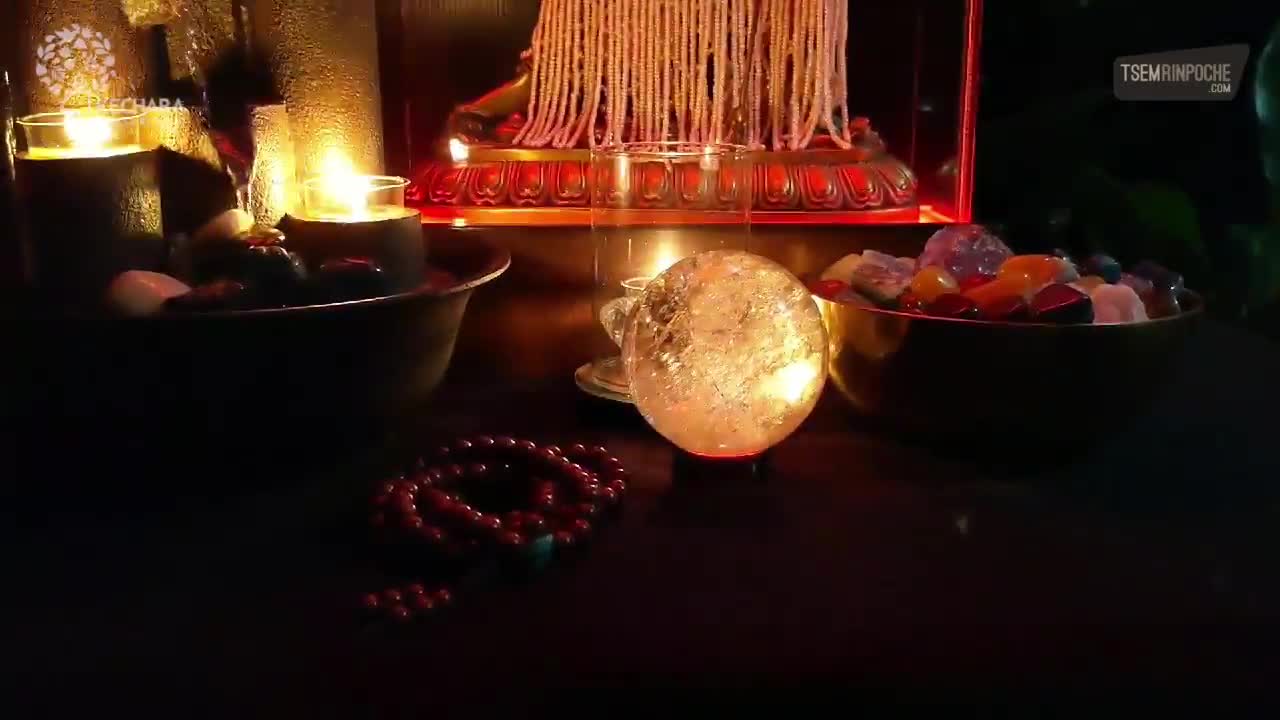











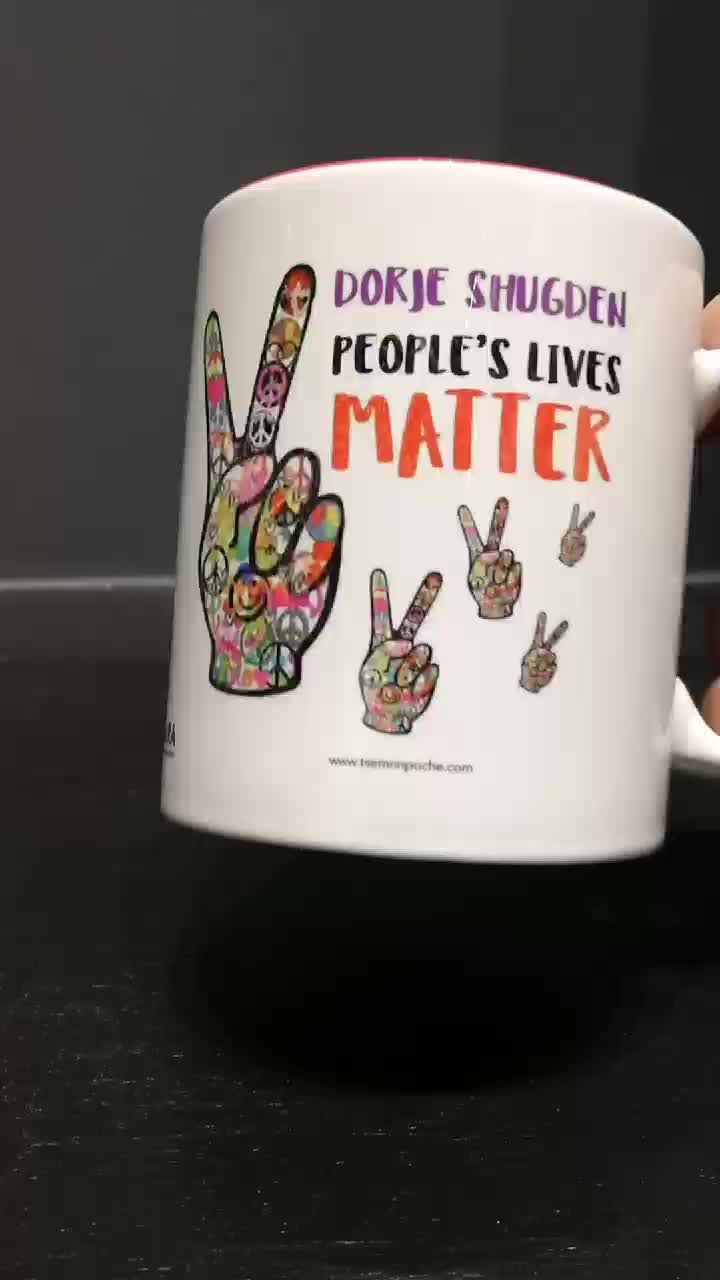

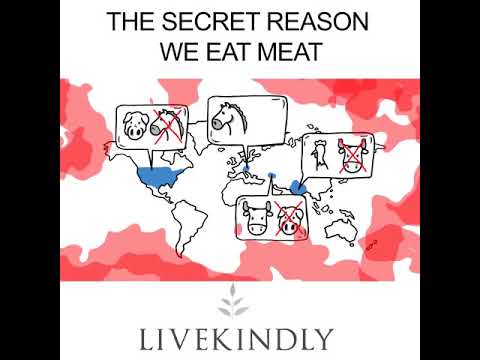


































































DISCLAIMER IN RELATION TO COMMENTS OR POSTS GIVEN BY THIRD PARTIES BELOW
Kindly note that the comments or posts given by third parties in the comment section below do not represent the views of the owner and/or host of this Blog, save for responses specifically given by the owner and/or host. All other comments or posts or any other opinions, discussions or views given below under the comment section do not represent our views and should not be regarded as such. We reserve the right to remove any comments/views which we may find offensive but due to the volume of such comments, the non removal and/or non detection of any such comments/views does not mean that we condone the same.
We do hope that the participants of any comments, posts, opinions, discussions or views below will act responsibly and do not engage nor make any statements which are defamatory in nature or which may incite and contempt or ridicule of any party, individual or their beliefs or to contravene any laws.
Please enter your details